Abdurrahman Wahid Menjawab
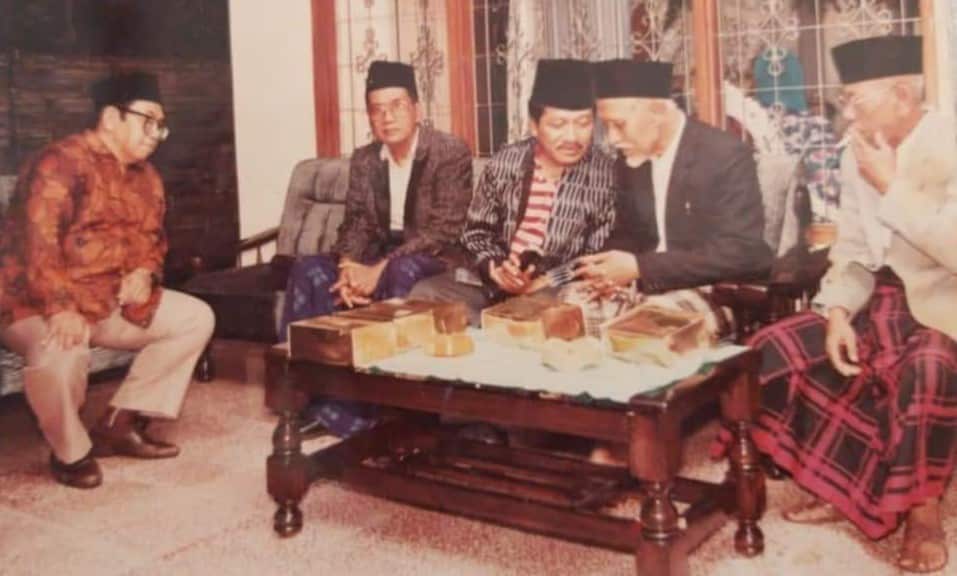
Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid
I. Pendahuluan (Penjelasan tentang Khitthah)
Sebelum menangkis “gugatan” Gus Dur terlebih dulu menyampaikan penjelasan panjang lebar mengenai kihttah NU:
Pernyataan terpenting tentang “Keputusan Kembali kepada Khitthah NU 1926” adalah bahwa keputusan itu tidak diambil untuk berhenti, melainkan bahwa prinsip-prinsip di dalam Khitthah itu harus dikembangkan terus. Oleh karena itu dari satu Muktamar lainnya, harus dilakukan tinjauan terhadap cakupan (ithaar) Khitthah kita. Sejauh manakah cakupan pada tahun 1984 yang intinya adalah bagaimana mengembalikan Nahdlatul Ulama pada pemikiran keagamaan murni? Lalu bagaimanakah mengaitkan pemikiran murni itu dengan tugas-tugas kemasyarakatan? cara berpikir menurut paham Aswaja yang mempunyai karakteristik tersendiri mesti dikembangkan menjadi sejumlah kegiatan yang didukung oleh Khitthah, yang intinya adalah:
1) Penataan organisasi secara tuntas,
2) Peningkatan pendidikan,
3) Peningkatan dakwah dan
4) Peningkatan mutu kehidupan (tahsin mustawal-ma’isyah) warga Nahdlatul Ulama.
Namun tentunya, para Muktamar ke XXVIII tahun ini, patut dipertanyakan keluasan cakupan di atas. Sebab Nahdlatul Ulama tidak berada di dalam suatu keadaan kosong (vacuum), melainkan di dalam kehidupan sebuah bangsa yang berkembang. Ini menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri bagi Nahdlatul Ulama. Pada masa lalu (sebelum tahun 1984), tantangan ini adalah bagaimana Nahdlatul Ulama mengerem merosotnya nilai-nilai keagamaan di kalangan warganya karena banyak perilaku telah diverpolitisir, baik oleh kita sendiri maupun oleh orang luar. Harus diakui bahwa pada saat itu keadaan Nahdlatul Ulama telah sedemikian parahnya, sehingga andaikan kegiatan politik praktis dilanjutkan selama dua tahun lagi, organisasi ini kan seperti PPP, yang ketuanya dipilihkan oleh orang quar. Perkiraan demikian adalah wajar, sebab pemerintah merasa perlu menengahi kericuhan di dalam sebuah organisasi yang sangat berpengaruh pada skala nasional. Dan dengan campur tangan seperti itu, tamatlah riwayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mandiri.
Maka pencegahan pun dilakukan dengan melepaskan diri dari politik, dalam arti: pertama, secara organisatoris, Nahdlatul Ulama tidak terkait dengan kekuatan sosial politik mana pun kedua, mengembangkan pemikiran sunni ke arah empat kegiatan utama sebagaimana telah disebutkan di atas.
Untuk sementara, cakupan Khitthah sebagaimana berlaku tahun 1984-1989 di atas dianggap cukup. Ternyata warga Nahdlatul Ulama merasa harga dirinya dan rasa percaya dirinya naik kembali. Terutama Nahdlatul Ulama sendiri bisa menempatkan diri secara strategis di hadapan pemerintah, rakyat, organisas-organisasi kemasyarakatan lain dan kekuatan sosial politik. Nahdlatul Ulama bisa melayani pemerintah tanpa kehilangan kepercayaan rakyat. Problem di semua negara berkembang adalah ketika pemerintah melaksanakan pembangunan, ketika itu pula kepercayaan rakyat kepada pemerintah berkurang, sebagai akibat dari kekurang mampuan pemerintah mengembangkan mekanisme pengendalian diri (waskat). Pada gilirannya, pihak yang dinilai membela pemerintah akan dianggap tidak memahami rakyat. Kesulitan ini ternyata bisa diatasi oleh Nahdlatul Ulama. Mungkin, masyarakat masih amat percaya bahwa muru’ah para ulama mereka tetap tak luntur dari waktu ke waktu. Mereka, misalnya, membedakan perilaku ulama Nahdlatul Ulama dari ulama yang ada di lembaga lain yang terkesan gampangan dan tak tahu batas wilayah pekerjaan sendiri. Patut disyukuri antara lain, ketika MUI menghalalkan produk-produk yang dicurigai mengandung lemak babi, tak satu pun ulama Nahdlatul Ulama yang meminta PBNU mengambil sesuatu keputusan. Dari contoh ini tampak sekali bahwa ulama Nahdlatul Ulama tahu benar sampai di mana batas wilayah wewenangnya. Penentuan mengandung unsur lemak babi atau tidaknya suatu makanan adalah tugas ahli teknologi pangan. Ulama tinggal memberikan fatwa terhadap hasil penemuan mereka. Begitu pula, ulama Nahdlatul Ulama tidak pernah secara bersama-sama menyatakan dukungan 100% kepada pelaksanaan pembangunan. Mereka juga biasa mengajukan kritik di sana sini sambil diam-diam menerima bagian lain dari sisi pembangunan itu. Kritik yang mereka lancarkan sangat dirasakan keberadaannya oleh rakyat, meskipun dilakukan secara samar-samar.
Akan tetapi, sikap Nahdlatul Ulama ini memang terlihat segi kekurangannya, yaitu ketidakjelasan posisi yang diambilnya. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama jangan banyak berharap kepada siapa pun, termasuk kepada pemerintah. Bagi saya, yang terpenting Khitthah yang dilakukan sekarang adalah cocok dengan kebutuhan kita, yaitu memenuhi keinginan rakyat untuk melihat posisi ulama mereka yang sebenarnya, di mana Nahdlatul Ulama memang telah menyediakan posisi seperti itu. Tentu saja sebagai akibatnya, Nahdlatul Ulama berada pada tempat strategis. Organisasi ini menjadi dibutuhkan orang tapi tanpa terikat kepada siapa pun. Katakanlah sebagaimana ungkapan yang lebih kena, “ada di mana-mana, tapi tidak ke mana-mana”.
Dari sini kita berusaha membuat proyeksi (tawaqqu’at) ke masa depan. Yaitu apa tugas Nahdlatul Ulama setelah Muktamar ke XXVIII nanti (1990-1994)? Untuk itu yang terlebih dahulu harus dijawab adalah apa kebutuhan pada saat itu. Sebab pada tahun 1999, bangsa ini akan lepas landas dalam Pelita ke VI. Istilah “lepas landas” terdengar sederhana, akan tetapi mempunyai akibat yang sangat besar yang mencakup perubahan besar dalam cara hidup bangsa. Kita menjadi bangsa yang memasuki era industrialisasi besar-besaran. Nilai-nilai yang selama ini kita fahami akan terjungkir balik. Kalau Nahdlatul Ulama tidak mau bersiap-siap menghadapi masa itu, maka ia akan terjebak pada kegiatan mengurusi soal-soal yang tidak pokok dan meninggalkan soal-soal pokok. Jadi Muktamar ke XXVIII harus mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa warga Nahdlatul Ulama kepada masa persiapan menuju era lepas landas itu. Tantangan yang terbesar bagi bangsa ini harus kita rumuskan, misalnya berupa rumusan tentang wujud tantangan yang ditujukan kepada agama. Sementara saya melihat bahwa problem pokok tersebut adalah “di mana kedudukan syari’ah”. Sebab ternyata syari’ah sebagai sebuah keseluruhan tidak bisa diundangkan. Apa yang kita ikhtiarkan adalah bagian syari’ah yang mana yang mesti (perlu) diundangkan, dan bagian mana pula yang cukup dibiarkan saja menjadi etika (akhlaq) masyarakat. Misalnya, kewajiban shalat Jum’at tidak perlu diundangkan tetapi cukup diajarkan dalam pengajian.
Era lepas landas menuntut beberapa persyaratan di luar bidang “agama”. Persyaratan pertama, pertumbuhan ekonomi harus tetap tinggi. Pertumbuhan yang tinggi hanya mungkin jika ada efisiensi serta kemampuan untuk mengelola segala sumber daya sebaik-baiknya. Efisiensi berarti antara lain kemampuan untuk mengekspor sebanyak-banyaknya dan menyediakan kebutuhan dalam negeri semurah-murahnya. Efisiensi ini diperlukan untuk bersaing dalam percaturan ekonomi internasional. Efisiensi memerlukan obyektivitas (maudlu’iyyah), berupa ukuran-ukuran yang jelas untuk memastikan adanya hak dan kewajiban tertentu. Untuk melindungi obyektivitas diperlukan keadilan dan kepastian hukum. Artinya, akan tiba saatnya, misalnya, ketika seseorang terbukti secara formal tidak berhak menjabat suatu jabatan yang dipegangnya, maka ia akan ditindak oleh pengadilan berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh orang yang mersa memenuhi persyaratan formal. Tiap pelanggaran, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, bisa dituntut ke pengadilan.
Keadilan hukum membutuhkan kedaulatan hukum, bukan kehendak satu dua orang penguasa. Kedaulatan hukum berarti hak untuk berbicara secara bebas. Hak berbicara secara bebas membuahkan mekanisme konltrol atas pemerintah secara efektif, kontrol sosial.
Kebutuhan-kebutuhan masa depan ini saling bertalian. Pertanyaan inti yang kemudian muncul adalah bagaimana Nahdlatul Ulama turut menyumbang ke arah terpenuhinya kebutuhan bangsa itu, tanpa mengganggu stabilitas nasional? Sebab, selama ini belum ada satu pihak pun yang sanggup melakukannya. Setiap usaha ke arah demokratisasi pasti menimbulkan konflik sengit. Kalau Nahdlatul Ulama sanggup memberikan sumbangan itu, yang bahkan secara teoritis pun pada saat ini mustahil dicapai, maka negara ini akan menjadi milik Nahdlatul Ulama. Sebab semua pihak akan memberikan dukungannya, termasuk pemerintah yang pasti akan menyam-paikan rasa terima kasihnya. Tapi untungya, proses sosial memang tidak harus persis sama dengan teori. Kalau Nahdlatul Ulama berhasil 75† saja dari keseluruhan petunjuk teori, maka sudah merupakan sebuah prestasi yang sangat bagus.
Jika Muktamar yang akan datang melalaikan tugas ini, maka artinya Nahdlatul Ulama hanya bermain-main dan tidak mau mengerti bahwa dirinya hidup di tengah-tengah suatu bangsa yang nyata-nyata ada.
II. Jawaban
Apa yang akan saya kemukakan bukanlah merupakan jawaban, tetapi lebih merupakan klasifikasi (tabayyun). Seluruh “gugatan” yang disampaikan pimpinan akan saya kelompokkan menjadi “kelompok pemikiran” dan “kelompok tindakan”. Yang sebenarnya tak memerlukan penjelasan panjang lebar.
A. Kelompok Tindakan
1. Menjadi Ketua DKJ
Saya menjadi Ketua DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) sebelum menjadi Ketua PBNU. Secara organisatoris, berhenti dari DKJ tidak bisa dilakukan begitu saja, sebab harus menghabiskan masa jabatan. Hal ini ada kaitannya dengan masalah laporan pertanggungjawaban pula. Masa jabatan ini habis tepat ketika saya menjabat Ketua PBNU selama enam bulan.
Saya menjadi Ketua DKJ karena ada permintaan agar ada di antara orang pesantren yang mengurusi para seniman dan bukan hanya mengurusi pesantren saja. Mengurusi seniman memang mengandung risiko berat, sebab perilaku dan sikap mereka umumnya anch-anch. Akan tetapi saya melihat bahwa sebagian seniman mulai memahami agama, hingga sayang sekali jika tidak mendapatkan perhatian dari kalangan pesantren. Di samping itu, pernyimpangan-penyimpangan dalam dunia seni mesti diluruskan secara langsung dari dalam. Di sini harus dibedakan antara menjadi seniman dengan mengelola kesenian. Yang saya lakukan adalah mengelola kesenian. Hasil pengelolaan itu ternyata menimbulkan harapan dan kegembiraan di kalangan para pengambil keputusan di negeri ini, termasuk Menteri Penerangan Harmoko dan Gubernur DKI saat itu. Harmoko misalnya mengatakan kepada saya bahwa ukuran moral dalam perjurian film sangat simpang siur. Misalnya sebuah film bisa memenangkan kejuaraan, padahal di dalamnya dikisahkan seorang yang mencuri istri orang lain dan bebas, sukses tanpa hukuman.
Untuk melakukan pembenahan, saat itu saya menghubungi H Misbach Yusach Biran dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa untuk bisa mengusahakan pemantapan kriteria perjurian, seseorang minimal harus terjun secara langsung dalam perjurian sebanyak tiga kali. Dengan mengucapkan “bismillah” saya terjun langsung. Dan ini terjadi sebelum saya menjadi Ketua PBNU. Memang K.H. As’ad Syamsul Arifin mensyaratkan agar saya melepaskan kegiatan di DKJ. Saya taat, meskipun banyak teman melepaskan kepergian saya dengan perasaan berat.
2. Membuka Malam Puisi Yesus Kristus
Sebuah peristiwa yang menimbulkan kehebohan adalah ketika saya membuka Malam Pusis Yesus Kristus. Buntutnya, saya dikafirkan oleh Habib Jamalullail dari Kernolong Kramat, Jakarta. Saya sampaikan jawaban ketika saya menghadiri pengajian di Masjid Raden Saleh, yang tidak jauh dari tempat tinggal beliau. Saya katakan: pertama, malam puisi bukanlah acara ibadah. Sedangkan yang diharamkan adalah hadir pada acara ibadah pemeluk agama lain. Lahkan masuk gereja ketika sedang melaksanakan peribadatan, sedang kita tidak mempunyai kaitan dengan ibadah itu, hukumnya tidak haram. Hanya persoalan muru’ahlah yang mengajarkan agar perbuatan itu tidak dilakukan. Kedua, nama Yesus Kristus hanya sekedar nama yang tak harus berisi akidah tertentu. Yesus adalah nama dalam salah satu Bahasa Eropa yang mempunyai akar dalam Bahasa Siryani. “Esu” dalam Bahasa Arab adalah “Isa”. Nama Kristus berasal dari bahasa Yunani kuno, “Kristos”, yang berarti “juru selamat”, yang dalam Bahasa Arabnya adalah “Al-Masih”, istilah yang juga dipakai oleh Alqur’an sendiri. Soal i’tiqad yang dikandung oleh kedua kata itu, terserah kepada yang mengucapkannya. Tentu saja, ketika saya mengucapkan Yesus Kristus, akidah yang ada dalam hati saya adalah Ahlussunnah.
Sampai tujuh kali saya secara terbuka menyampaikan jawaban seperti ini dalam berbagai pengajian, akhirnya Habib Jamalullail berkirim surat agar polemik diakhiri.
3. Target dan Hasil di DKJ
Alhamdulillah, pada saat ini, para seniman adalah pembela Islam yang tangguh. Misalnya saja dalam kasus “Ayat-ayat Setan” Salman Rusdhie, Danarto (seorang seniman) mengatakan bahwa sebagai orang yang ber-Tuhan, dia takut kepadaNya dan tidak akan berani berbuat seperti Salman Rushdie. Syu’bah Asa, seorang penulis essay terbaik, mengatakan bahwa selama umat Islam masih ada, tidak akan mungkin menggambarkan Nabi dan keluarganya seperti yang digambarkan Salman Rushdie. Malahan justru saya yang lebih “liberal” seraya mengatakan bahwa Salman Rushdie dan bukunya adalah salah dan kurang ajar. Biar saja ia dihukum Allah sendiri, dan kita tidak perlu terlalu risau. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa membaca “The Satanic Verses” adalah tak apa-apa. Sebab saya yakin bahwa orang yang Islamnya benar tidak akan terpengaruh. Jika ada orang yang murtad sehabis membacanya, memang pada dasarnya ia telah ingin murtad sebelumnya dan tinggal menunggu alasan, apa pun bentuknya, kandungan novel itu atau yang lain. Saya berkata demikian agar Islam bisa diterima oleh semua pihak, termasuk oleh orang yang terbiasa dengan kebebasan berbicara yang mungkin menentang larangan terhadap sesuatu penerbitan.
Pengajian di kalangan seniman sudah berjalan dengan baik, dan tampaknya sangat berpengaruh pada keberagamaan mereka.
4. Menjadi Anggota MPR
Masalah keanggotaan saya di MPR sebenarnya masalah yang sederhana. Saya ditunjuk oleh Pak Harto dan sebenarnya saya berkeberatan. Saya perkirakan saya akan menghadapi kesulitan yaitu keharusan memilih fraksi, yang pilihan mana pun akan mengundang kecaman. Saya dipanggil Pak Sudharmono, yang saat itu adalah Menteri Sekretaris Negara, kata beliau, “Saya mengerti kesulitan sampeyan. Tарі ini tugas negara. Maka berdasarkan penjelasan ini saya membayangkan kengerian yang lebih hebat, seperti sangka buruk bahwa NU tidak mau mendukung pencalonan Pak Harto sebagai Presiden, kalau saya sampai menolak keanggotaan MPR itu. Maka saya terpaksa mengambil keputusan melalui kaidah dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jablil-mashalih, idza dlaa-qalamru ittasa’a dan sebagainya.
Saya pun masuk. Dan apa yang saya bayangkan benar-benar terjadi, yaitu betapa sulitnya memilih fraksi. Memilih PDI akan jelas menimbulkan kesan bermain-main. Memilih PPP saya khawatir dianggap membenarkan klaim bahwa NU wajib berafiliasi ke PPP. Maka saya terpaksa memilih Golkar. Terus terang saya tersiksa, membayangkan perasaan warga Nahdlatul Ulama. Bahkan di keluarga saya sendiri, saya menghadapi persoalan. Adik saya Korpri, yang pasti menyambut baik keputusan saya. Sementara itu, ibu saya adalah anggota Majelis Pertimbangan Pusat PPP, yang tentu merasa tidak setuju.
Kelanjutan dari kesulitan saya muncul pula ketika pernyataan internal saya tiba-tiba jebol di koran, yaitu berkenaan dengan rencana saya mengundurkan diri dari keanggotaan MPR. Datanglah utusan dari Sugeng Wijaya, anggota ABRI terkemuka yang ditempatkan di DPP Golkar. Pak Sugeng mengatakan bahwa jika saat itu saya mengundurkan diri, maka akan timbul kemelut baru. Saya akan disangka keluar dari FKP untuk merebut posisi Naro dalam Muktamar PPP bulan Agustus. Oleh karena itu, segala hal dalam soal ini saya bekukan dulu sambil melihat-lihat perkembangan.
Akan tetapi semua orang berpendapat sama, bahwa saya masuk menjadi anggota MPR lebih merupakan kesengsaraan daripada memperoleh suatu keuntungan. Oleh karena itu, persoalan ini tidak perlu diperpanjang lagi.
Secara keseluruhan, kira-kira saya menegang 16 jabatan di berbagai tempat. Untuk sebagaiannya adalah merupakan pengabdian. Sedang selebihnya saya rasakan sebagai suatu yang meringankan beban hidup, agar bisa antara lain lebih memusatkan perhatian kepada pengabdian saya melalui Nahdlatul Ulama.
B. Kelompok Pemikiran
1. Bermadzhab
Pokok dari cetusan pemikiran, saya adalah pendirian saya yang mungkin berbeda dengan kebanyakan kaum Nahdliyin tentang aqidah Ahlussunnah dan bermadzhab. Dalam soal ini, saya ingin sekali difahami mengapa saya berbeda. K.H. Masduqi Ali, misalnya, menyatakan bahwa dalam bermadzhab Syafi’i, beliau mengambil pendapat-pendapat Syafi’iyah yang kuat dan ahwath. Tetapi saya berpendapat bahwa mengkuti madzhab Syafi’i bisa berarti mengikuti Imam Syafi’i dalam manhaj (metode) peng-galian hukum (ushul-fiqh dan qa’idah fiqhiyah). Oleh karena itu kita memang harus terus menerus merumuskan konsep tentang bermadzhab ini. Dan risikonya memang akan muncul pendapat-pendapat yang berbeda dengan yang populer sekarang. Akan tetapi hal ini perlu sekali agar Nahdlatul Ulama mampu berdialog dengan “orang lain” tanpa kehilangan inti dirinya.
Sebenarnya secara diam-diam, Nahdlatul Ulama sendiri sudah mulai menuju kepada rumusan tentang bermadzhab sebagai “mengikuti manhaj”, dan bukan sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi (aqwal). Sebagai contoh, keputusan Muktamar (bahtsul masail) selalu menyebutkan alasan dan segi-segi istidlal dari suatu pendapat yang diambil.
Di sini kita menjadi sadar bahwa kita sudah tidak bisa lagi memaksa masyarakat mengikuti saja pendapat kita tanpa berfikir, khususnya di kalangan generasi muda. Tentu saja Nahdlatul Ulama tidak patut membiarkan mereka berpindah ke tempat lain hanya karena di sana mereka bisa mendapatkan kualitas pemahaman yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kita harus melakukan kaji ulang terhadap sikap-sikap kita. Dan kita harus siap menghadapi risiko yang pasti akan muncul.
2. Mu’tazilah dan Syi’ah
Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa “memahami” pendapat golongan lin berbeda dengan “menerima”nya. Oleh karena itu saya tidak rela jika dikatakan telah terpengaruh oleh pikiran-pikiran Mu’tazilah maupun Syi’ah, sebab saya hanya berusaha memahami saja. Saya mengatakan bahwa Mu’tazilah mempunyai konsep keadilan yang mutlak Sementara kaum Sunni tidak pernah memberikan perhatian terhadap issue keadilan ini seserius mereka. Padahal secara terpencar-pencar, kitab-kitab Sunni telah menyinggungnya, seperti dalam ketentuan tentang syarat-syarat menjadi Kepala Negara, Hakim dan sebagainya. Sebagaimana telah diketahui, Mu’tazilah mempunyai “Lima Prinsip” (al-mabadi’ al-khamsah), setara dengan Rukun Iman dan Rukun Islam milik kaum Sunni. Saya hanya menyoroti “Prinsip Keadilan” (al-adalah) milik mereka, sebab keempat prinsip lain jelas salah di mata kaum Sunni, seperti prinsip Al-wa’du walwa’id yang seolah-olah mendikte Tuhan. Akan tetapi dalam prinsip ‘adalah, Mu’tazilah tidak bisa begitu saja dianggap salah. Bahkan kaum Sunni wajib berfikip pula tentang keadilan. Meski tidak sampai menempatkan prinsip keadilan pada posisi rukun agama, tapi kaum Sunni wajib menjabarkan konsep keadilan ini ke dalam keseluruhan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam.
Mengenai masalah Imamah, saya ingin mengajukan koreksi. Saya tidak membenarkan konsep imamah tersebut, melainkan mengatakan bahwa imamah adalah salah satu prinsip Syi’ah.
Syi’ah sebagai sebuah aliran aqidah, jelas bertentangan dengan aqidah Sunni. Akan tetapi sebagai wujud budaya, Syi’ah berisi “kecintaan kepada keluarga Nabi”, yang juga merupakan salah satu ciri utama Nahdlatul Ulama. Jadi secara kelakar bisa dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah Syi’ah kultural.
3. Memperbanyak Titik Temu
Dalam berbagai kesempatan menerangkan “paham lain”, sebernarnya saya ingin memperbanyak titik temu di antara berbagai golongan dalam Islam, bukannya menonjolkan perbedaan. Kita mesti mengingat kembali bahwa perbedaan antar Imam pada zaman dahulu lebih banyak tentang aqidah. Meskipun demikian, di antara mereka terjadi pergaulan yang wajar dan bahkan hangat. Misalnya, Imam Ghazali begitu akrab dengan Imam Ibn Babawaih al-Qummi, ulama Syi’ah. Dan pada kenyataanya, Hukum Antar Golongan dalam fiqh Islam tidak menaruh perhatian kepada soal hubungan antar madzhab ini. Misalnya, tak ada masalah di sekitar perkawinan pengikut Sunni-Syi’ah. Malahan yang agak kaku justru Hukum Antar Golongan milik Syi’ah. Hal ini bisa dilihat dalam Fatawa-Alamghiri di India. Orang Syi’ah biasa menyebut dirinya orang mu’min, sedang kaum Sunni disebutnya orang “muslim”. Fatawa Alamghiri menetapkan bahwa “mu’min” tidak boleh menikah dengan “muslim”, tetapi sebaliknya, “mu’minah” tidak boleh menikah dengan “muslim”. Jadi rupanya, orang Syi’ah memandang Sunni seperti memandang Ahli Kitab.
Harapan saya, akan terjadi penyempitan jarak antara Sunni dan Syi’ah dalam bidang non-aqidah. Sebab, pokok aqidah Syi’ah memang telah mapan semenjak Syaikhul Mufid mengatakan bahwa aqidah Syi’ah mempunyai prinsip yang serupa dengan prinsip Mu’tazilah. Syi’ah mengganti prinsip “al-manzilatu bainal-manzilatain” dengan prinsip “imamah” Memang sebelum itu, guru Syaikul Mufid, yaitu Ibn Babaiwaih al-Qummi, merumuskan aqidah Syi’ah yang lebih mirip kepada aqidah Sunni yang ditambah dengan imamah. Sepeninggal Ibn Babawaih, Syaikhul Mufid banyak berguru kepada tokoh Mu’tazilah.
4. Rukun Tetangga
Pada intinya, saya terus menerus merasa risau kenapa umat Islam tidak begitu peduli dengan masalah-masalah sosial, padahal ayat-ayat tentang itu demikian banyak dan jelas. Mengapa misalnya perjuangan dengan harta tidak banyak dilakukan, padahal hampir dalam semua ayat tentang jihad, perjuangan dengan harta benda disebut lebih dahulu sebelum jihad dengan jiwa (perang). Pertanyaan demikian terutama saya ajukan kepada kalangan Nahdlatul Ulama sendiri. Padahal kalangan muda Islam sedang serius berfikir tentang soal-soal sosial ini. Beberapa waktu yang lalu misalnya, Moeslim Abdurrahman mmenemukan kasus dalam penelitiannya di Belanakan (Subang). Di tempat itu para haji yang kaya membangun masjid-masjid yang megah atas swadaya masyarakat. Para haji itu menikmati kesempatan yang cukup untuk beribadah di masjid, sementara buruh tambak mereka harus berangkat pukul 03.00 pagi untuk bekerja dan mereka tidak bisa melaksanakan shalat shubuh. Moeslim bertanya, “Bagaimanakah nasib buruh itu di akhirat, padahal masjid-masjid itu dibangun dari cucuran keringat mereka? Apakah begitu saja diputuskan bahwa pak haji masuk surga dan buruh masuk neraka?”
Terus terang, persoalan seperti ini meluas sekali di masyarakat, dan orang Islam belum bisa memberikan perhatian yang sewajarnya. Perbedaan taraf ekonomi di kalangan Ahlussunnah sendiri sangat besar. Mungkin di Indonesia tidak demikian gawat. Tetapi di negara lain, seperti Mesir, persoalan itu demikian mencolok. Di satu pihak orang memiliki tanah puluhan ribu hektar, sementara orang lain tak punya apa-apa. Lalu dilaksanakanlah land-reform. Tapi serta merta ulama melancarkan tentangan, padahal maksud dari kebijaksanaan land reform adalah menyamakan keududukan manusia di muka hukum, agar perbedaan sikaya dan si miskin tidak terlampau jauh. Sebeb lebarnya jurang pemisah ini akan sangat menguntungkan kaum komunis. Saya lalu “menemukan” sebuah ayat yang sangat relevan dalam masalah ini yaitu Surat Al Baqarah ayat 177. Ayat tersebut berbunyi laissal-birra antuwalluu wujuuhakum qibalal-masyriqi wal-maghribi walaakinnal-birra man aamana billaahi wal-yaumil aakhiri wal-malaa’ikati wal-kitaabi wan-nabiyyin, wa aatal-maala ‘alaa hubbihi dzawil-qurbaawal-yataamaa wal-masaakiini wa-bnis-sabiili was-saa’iliina wafir-riqaabi wa aqaamash-shalaata wa aataz-zakaata wal-muufuuna bi’ahdihim idzaa ‘aahaduu was-shaabiriina fil-ba’saa’i wadi-dlarraa’i wa biinal-ba’si. Ulaa’ikal-ladziina shadaquu waulaa’ika humul-muttaquun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang merninta-minta, dan memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. Terjemahan Departemen Agama).
Setelah menilik ayat tersebut, saya lihat bahwa persoalan yang sangat perlu pemecahannya adalah keterpisahan antara dua komponen dalam sistem keyakinan Islam, yaitu keyakinan akan keimanan yang sangat pribadi, sebagaimana yang tercantum dalam Rukun Iman dan dimensi sosialnya sebagaimana tercantum dalam Rukun Islam. Pada dimensi individu, ukuran keimanan bersifat sangat pribadi dan merupakan urusan seseorang dengan Allah sendiri (hablun minallah). Sedang pada dimensi sosialnya, syahadat yang tampak bersifat sangat pribadi itu ternyata berwawasan sosial, karena pengucapannya harus dilakukan di muka orang banyak, seperti dalam persaksian perkawinan. Apalagi tentang Rukun Islan yang lain. Shalat, apalagi berjamaah, berfungsi mencegah perbuatan keji dan munkar, yang berarti berorientasi menjaga ketertiban masyarakat. Sementara zakat telah jelas sebagai ibadah sosial, puasa adalah keprihatinan sosial dan ibadah haji adalah saat berkumpulnya kaum muslimin dari segala penjuru dengan berbaju ihram yang sama tanpa memandang pangkat dan kedudukan. Persoalannya kini adalah bagaimana dimensi pribadi ini bisa diterjemahkan secara sosial, Karena di kalangan umat Islam ternyata banyak orang menjadi muslim yang baik dan sekaligus menjadi mahkluk a-sosial. Sebaliknya, bisa berbentuk pula sikap hidup yang begitu sosial tetapi tanpa keimanan. Usaha menjembatani kedua bentuk keberagamaan yang ekstram ini adalah sebuah keharusan. Ayat tadi telah memberikan petunjuk, bahwa struktur masyarakat yang adil harus ditandai dengan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan orang-orang yang menderita dan pengerahan dana untuk membela kaum lemah. Secara epistemologis, konsep ini belum pernah dirumuskan dan disepakati sebagai soal teologi, melainkan dianggap sebagai soal politik. Dengan demikian yang masih diperlukan adalah pengembangan akidah Islamiyah yang mempunyai komponen Rukun Iman dan sekaligus Rukun Islam dalam bentuk yang terjembatani.
Usaha menjembatani ini merupakan pekerjaan besar yang saya namakan Rukun Tetangga itu. Memang dalam hadits hanya disebutkan dua rukun saja. Tetapi hadis tersebut tidak sampai melarang dijadikannya apa yang ada di antara keduanya, sebagaimana tersebut dalam ayat tadi, sebagai masalah pokok dalam agama. Saya pakai kata “rukun” untuk menunjukkan artinya yang sangat penting. Dan untuk menunjukkan bahwa itu tidak sampai menjadi rukun agama, maka saya ambil kata “tetangga” Kata “tetangga” jugta bisa digantikan dengan kata “sosial”.
Mungkin orang akan mengatakan bahwa masalah sosial dicukupi oleh ajaran tentang zakat. Akan tetapi bagi saya, pengelolaan zakat selama ini belum mampu menyelesaikan persoalan kemasyarakat secara umum, melainkan “hanya” menyucikan harta, merupakan tanda keikhalan kita kepada Allah. Dengan bahasa lain, zakat sama dengan “memberi ikan” (tabarru), sedang memecahkan masalah sosial adalah “memberi pancing”. Oleh karena itu saya tolak sama sekali pendapat bahwa zakat sama dengan pajak. Begitu pula, saya berpendapat bahwa pengembangan zakat menjadi zakat produktif adalah masih diperlukan kajian. Saya katakan, silakan melakukan upaya-upaya meningkatkan produktivitas, tetapi pakailah sumber dana lain di luar zakat. Lagi pula zakat dalam pelaksanaan yang kita kenal, sangat membuka peluang terjadinya akal-akalan (hilah), terutama dalam ketentuan tentang haul dan nishab.
Berdasarkan pemikiran ini, saya memandang perlu dikembangkannya kerangka teori sosial. Tentu saja seruan ini bertolak dari pendapat bahwa umat Islam belum mengembangkan teori sosial yang konsepsional. Ternyata pendapat terakhir ini menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam. Saya didakwa tidak mempercayai bahwa Islam telah sempurna. Padahal sebenarnya kesempurnaan Islam barulah dalam bentuk penetapan prinsip-prinsip. Buktinya kita masih perlu menjabarkan nash menjadi hukum-hukum yang terinci. Dan dalam rangka penjabaran ini, pemikiran tentang Islam akan terus menerus berkembang. Bahkan menurut sebagaian mufassirin, arti kata “akmaltu” dalam ayat 3 Surat al-Maidah bermakna “anhaitu”, yaitu bahwa dalil-dalil keagamaan sudah tidak akan turun lagi. Dan kalau mau “kurang ajar”, penafsiran ini bisa dilanjutkan bahwa firman itu menyuruh “selanjutnya pakailah pikiranmu sendiri”. Tapi bagi saya, prinsip-prinsip yang telah dibakukan dalam Al-qur’an ada tiga, yaitu persamaan (al-musawah), musyawarah (asy-syura) dan keadilan (‘adalah).
Dari prinsip ini lalu bisa dikembangkan menjadi teori sosial. Dan tentu saja, hasil dari pengembangan ini hanya berlaku pada masa danm tempat tertentu. Sedang yang berlaku terus adalah “apa yang disepakati oleh jumhur atau seluruh ulama” (ijma’). Sebagai contoh, tidak ada ijma’ tentang bentuk negara, kekuasaan imam (kepala negara) dan sebagainya. Saya perlu menegaskan kembali bahwa pada dasarnya, teori sosial menurut Islam belum disusun. Sedangkan yang digunakan selama ini barulah “wawasan” Islam. Wawasan adalah “pandangan” (ra’yu). Sedangkan teori mestilah merupakan pemikiran yang bulat dan utuh.
Sebagai contoh dari kekosongan teori sosial bahwa ummat Islam belum pernah merumuskan secara bulat, utuh dan terinci tentang hubungan antara individu dengan negara. Misalnya tidak pernah dirinci antara individu dengan negara. Misalnya tidak pernah dirinci sampai sejauh mana rakyat harus taat kepada penguasa. Selama ini yang kita kenal hanyalah “tak perlu taat terhadap sesuatu perintah yangt merupakan kedurhakaan (ma’siat) kepada Allah”. Sementara itu, di dunia ini telah berkembang dengan pesat teori-teori sosial, seperti komunis, dan kapitalis. Memang sementara cendekiawan muslim telah berusaha menyusunnya, akan tetpai selama ini hasil yang mereka capai barulah merupakan pendapat perorangan, belum menjadi kesepakatan, sehingga belum tentu bisa dikatakan sebagai teori Islam. Misalnya konsep wilayatulah-faqih yang dirumuskan oleh Khomeini adalah teori kenegaraan sebab setidaknya telah mengandung dua hal, yaitu bentuk negara dan proses penggantian kekuasaan. Di dalamnya disebutkan bahwa bentuk negara adalah jumuhuriyah (republik), di mana fuqha menempati kedudukan tertinggi. Mereka tergabung dalam Dewan Fuqaha yang juga dinamakan maraji’ ad-din al-‘ulya (sumber agama yang luhurl), yang keputusan mereka mengikat negara. Teori ini jelas berbeda dengan kapitalisme, di mana tidak ada kekuasaan yang diteirma di luar kekuasaan negara. Juga berbeda dengan komunisme, di mana kekuasaan tertinggi di pegang oleh partai.
Meskipun demikian, susunan Khomeini belum bisa dikatakan sebagai teori Islam, sebab masih sekedar merupakan pemikiran pribadinya, yang jika bisa diterapkan toh hanya berlaku di Iran saja, tidak di negara Islam lainnya, Di Arab Saudi, raja memegang kekuasana tertinggi, sementara ulama hanya menjadi penasihat dengan fungsi konsultatif saja. Di sana juga tidak ada wakil rakyat semacam DPR. Sedangkan di Pakistan, aga gabungan antara kekuasaan presiden dan perdana menteri, sebagaimana yangd iterapkan di Perancis. Semuanya menamakan diri negara Islam, tetapi kita tidak bisa segera memastikan mana di antara ketiganya yang benar-benar Islam. Pernyataan bahwa umat Islam tidak/belum mempunyai teori sosial maupun kenegaraan tidak mengganggu keyakinan tentang kesempurnaan Islam. Sebab, prinsip-prinsip yang mempunyai nilai kebenaran abadi telah secara lengkap dibakukan. Dari sini lalu dibuatlah teori-teori yang di antaranya bisa berlaku terus, dan di antaranya bisa diubah sewaktu diperlukan.
Teori sosial yang saya inginkan penyusunannya itu nantinya akan menyediakan tempat yang sebenarnya bagi upaya-upaya pembebasan masyarakat dari penjajahan dalam segala bentuk dan keterbelakangan serta kernlaratan. Sebab, ketiganya sebenarnya hanya merupakan akibat saja dari struktur masyarakat yang pincang. Misalnya, yang menetapkan ganti rugi penggusuran rumah, tanah, dan sebagainya adalah pemerintah atau DPR yang diandaikan sebagai wakil rakyat. Dan, cara ini jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan, tetpai belum ada satu pihak pun yang mampu merubahnya.
5. Islam Indonesia
Saya ingin mengatakan, sebagaimana telah saya sebutkan dalam buku “Indonesia Kini dan Esok”, bahwa kaum muslimin perlu merubah pemahaman mereka terhadap ayat “wa lan tardlam ‘ankal yahuudu walan-nashaaraa hattaa tattabi’a millatahum“, berkenaan dengan sikap ke-Indonesiaan mereka.
Pertama, harus dijelaskan dari sudut mana hak-hak orang dibedakan. Dari sudut akidah, hak orang muslim berada di atas hak non-muslim. Tetapi Indonesia bukan negara Islam. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa hak nonmuslim di mata undang-undang negara adalah sama. Dan secara nyata itulah yang terjadi berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Sayangnya kita tidak pernah melakukan pembedaan itu.
Beberapa waktu yang lalu ada persoalan dalam penjelasan Undang-undang Pendidikan Nasional pasal 28, di mana PDI mempersoalkan bagian yang mewajibkan guru agama adalah penganut agama yang diajarkannya. Saya menolak pendapat PDI, sebab pendidikan agama menyangkut akidah Dan, tidak ada hak bagi nonmuslim untuk mendidik siswa yang muslim dalam bidang aqidah Islam. Tetapi saya berpendapat bahwa jabatan-jabatan kenegaraan boleh saja dijabat oleh nonmuslim ini, menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sedang kewajiban untuk berjualan agar semua jabatan diisi oleh umat Islam adalah soal lain, yaitu kewajiban agama. Masalah ini memang menuntut kecanggihan dalam memahaminya.
Kedua, ayat di atas sebenarnya menunjukkan hubungan Rasulullah dengan kedua kelompok itu (Yahudi dan Nasrani) di masa beliau. Jadi lebih anyak berbentuk sinyalemen bahwa tetanggamu, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang kurang ajar’ kepadamu. Engkau tetap dipaksa masuk agama mereka. Karenanya kau jangan berharap banyak dari mereka. Oleh karena itu, ketika ayat ini dianggap berlaku umum, timbullah masalah, antara lain kita wajib membuktikan alasannya. Sebab secara historis, konteks ayat itu tampaknya memang erat dengan peristiwa pengusiran beberapa suku yang hidup di Madinah, seperti Bani Quraizhah dan sebagainya.
Ketiga, pada saat ini, pemeluk agama lain sudah merumuskan kembali pola hubungan mereka dengan kaum muslimin. Misalnya, Konsili Vatikan ke-II pada tahun 1964, menghasilkan suatu putusan yang sangat fundamental. Yaitu gereja mengakui hak setiap orang untuk mencari kebenaran menurut cara masing-masing, meskipun sayangnya masih ditegaskan bahwa kebenaran terakhir hanya bisa dicapai melalui gereja Katholik Roma. Dari keputusan ini bisa dibaca bahwa mereka mampu berbicara dengan orang lain dengan tetap mempertahankan pendirian. Apa pun maksud mereka, kita harus memperhitungkan (bukan menerima) perkembangan ini. Jangan sampai timbul kesan bahwa orang lain bersikap luwes, tetapi kita bersikap kaku. Biar pun kita tak punya pilihan lain kecuali menolak bentuk-bentuk tawaran tertentu, marilah penolakan itu kita sampaikan secara luwes pula, dengan kesanggupan dan kesediaan untuk tetap bertukar pikiran. Dengan demikian akan terbukti secara nyata bahwa Islam memang bersifat dinamis, yang hidup, dan mampumenampilkan pendiriannya dalam hujjah-hujjah yang masuk akal, bukan agama yang sempit pandangan.
6. Assalamu ‘alaikum
Kehebohan dalam soal ini sebenarnya bermula dari suatu kejadłan yang sederhana pula. Saya telah diwawancarai oleh wartawan “Amanah” selama lima jam dalam bulan puasa. Dalam penyajiannya, hyasil wawancara itu dipotong, mungkin terlalu panjang. Akan tetapi, pemotongannya itu dilakukan justru tepat pada bagian yang paling penting. Saya mengatakan bahwa di antara problem yang dihadapi oleh umat Islam adalah bagiamana mempertemukan antara budaya (‘adah) dengan normal (syari’ah), sebagaimana juga menjadi persoalan dalam ushul fiqh. Saya katakan, pada dasarnya harus diupayakan titik temu yang sebesar-besarnya antara keduanya. Saya mengambil contoh tentang arsitektur masjid Indonesia kuno yang selalu mempunyai atap tiga lapis, sebagaimana yang sekarang dipopulerkan lagi oleh masjid bantuan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Atap tiga lapis ini menggambarkan iman, Islam, dan Ihsan. Tiga lapisnya sendiri sebenarnya diambil oper dari simbolisasi (perlambangan) dari masa Hindu-Budham, yaitu lapis sembilan, sebagaimana banyak dilihat di Bali. Simbolisasi sembilan ini menggambarkan sembilan glingkaran hidup manusia (reinkarnasi). Oleh Wali Songo, sembilan lapis itu disisakan tinggal tiga saja dan di sertai dengan penggantian maknanya, Artinya mereka mengambil bentuk budayanya saja, tetapi memberi isi lain yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Walisongo telah membuat penyesuaian pelan-pelan, dan tidak langsung membuat sesuatu yang sama sekali baru.
Contoh lain adalah adat yang berkembang di sekitar hari pasaran. Sebenarnya Islam tidak mengenal Wage, Kliwon, Legi, dan sebagainya, tetapi kemudian terjadi perpaduan, di mana hari yang dianggap lebih mulai dari yang lain adalah hari Jumat Legi. Perpaduan ini tidak melanggar syara’, tetapi bisa ngemong kebudayaan lokal.
Namun ada beberapa hal yang tidak bisa diperlakukan begitu saja seperti contoh di atas. Misalnya ketentuan tentang salam. Memang secasra budaya, assalamu ‘alaikum hanyalah sekedar ucapan berbaik-baik jika bertamu orang. Karena itu, secara budaya, ucapan salam ini bisa digantikan dengan “selamat pagi” dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa di dalamnya terdapat dua soal yang menyangkut norma. Pertama, memang memulai salam tidak wajib, tetapi menjawabnya adalah kewajiban, yang karenanya ucapan ketika menjawab tidak bisa digantikan dengan ucapan lain selain yang telah ditetapkan. Kedua, ucapan salam merupakan bagian tak terpisahkan dari shalat
Penjelasan terakhir inilah yang terpotong yang disajikan adalah con-toh tentang budaya saja, sedang sisi normanya terpotong. Terjadilah kehebohan, dan saya pun menyampaikan penjelasan ulang di majalah yang sama. Tapi pada umumnya, orang tidak membaca penjelasan kedua itu.
Saya tetap mengimbau agar kita menghargai budaya melalui sebuah upaya pribumisası Islam. Intinya bagaimana sebanyak mungkin menyerapkan adat dan budaya lokal ke dalam Islam. Sebagaimana telah dilakukan oleh para wali zaman dahulu. Misalnya, kita toh sudah biasa melihat bunga-bunga ditaburkan di makam, yang dicap sebagai bid’ah oleh kalangan tertentu. Padahal tak ada maksud lain kecuali ngemong kepada cara penguburan sebelum Islam. Demikian hitungan dari selamatan orang meninggal. Praktek-praktek ini kita jadikan sebagai wadah dari ibadah, atau dasar fadla-ilul a’mal.
Jika kita menolak melakukan pribumisasi, maka kita lebih mundur dari prestasi para wali. Hal ini menyebabkan Islam tidak bisa melayani dunia di luar pesantren. Lanjutannya adalah dunia luar akan direbut oleh orang lain. Saat ini sudah didirikan “pesantren Al-Kitab” oleh orang-orang Katholik. Mereka melihat ada kesempatan untuk masuk melalui budaya lokal, sementara kita sendiri lupa bahwa pesantren merupakan hasil dari perkembangan budaya lokal itu. Bahkan kata “pesantren” sendiri tidak terdapat dalam kamus Islam, melainkan sumbangan dari budaya lokal. Kata pesantren berasal dari kata santri, bahasa lokal, yang kemudian diambil oper dan diberi makna yang menunjukkan kegiatan mencari ilmu dan melaksanakan ibadah. Kata “santri” yang berasal dari bahasa Pali, “shan-tri”, berarti “ahli kitab suci” di masa sebelum Islam. Pada masa berikut-nya, ahli kitab suci Hindu Budha itu masuk Islam dan mempelajari agama ini dalam segala cabangnya di bawah bimbingan kyai. Kata “kyai” sendiri berarti “orang tua” (syaikh). Pemakaian kata “santri” dan “kyai” adalah hasıl dari pribumisasi Islam. Kalau kita saat ini hanya mau menggunakan kata “syaikh” dan membuang kata kyai, berarti kita melakukan kemunduran pula.
Di samping dalam bidang budaya, pribumisası juga harus diadakan dalam bidang hukum. Fat-hul Mu’in sendiri sebenarnya telah mengisyaratkan dimulainya usaha itu, misalnya dengan menyebutkan hukum mem akan kepiting, bekicot, dan sebagainya, yang sebenarnya hanya terjadi setempat.
Kadang-kadang pribumisasi juga berwujud perumusan kembali. Sebagai contoh, dan dipersilakan untuk tidak menyetujui pandangan yang saya sampaikan, ada hadits yang bermaksud memertintahkan kita melangsungkan perkawinan dan memperbanyak anak, sebab Rasulullah akan membanggakan kita nanti di hari kiamat. Penggantian yang selama ini populer adalah bahwa banyak anak dianjurkan oleh agama. Sedangkanm tentang rezeki anak-anak kita, kita mengikuti ayat tentang jaminan rezeki dari Allah bagi segala yang melata (daabbahg). Kesimpulannya, KB tidak perlu, atau malahan tidak boleh. “Saya mengajukan usul tentang model lain dari pemahaman nash-nash di atas. Merkea yang masih belum bisa menyetujui program KB saya persilakan untuk menerapkan pandangan-nya dalam sekala pribadi. Tetapi jika hendak dikaitkan dengan kepentingan bersama, saya mengajukan sebuah pertimbangan, yaitu segi yang akan dibanggakan oleh Rasulullah. Kita bisa bertanya apakah hanya jumlah yang banyak, ataukah kebanggaan itu juga mewajikan terpenuhinya persyaratan yang layak sebagai manusia, yang menyangkut pendidikan, sandang, pangan, dan sebagianya. Bagiamana mungkin akan ada perawatan yang baik jika kelahiran begitu sering dan banyak. Apa yang saya ajukan ini sudah bisa dikatakan sebagai pribumisasi Islam, di mana pada saat ini di Indonesia, kita lebih mengutamakan kualitas manusia, daripada kuantitasnya. Pribumisasi di sini berarti mengikuti jalan pikiran yang sedang berkembang di masa waktu tertentu.
Akan tetapi juga tidak begitu saja. Misalnya seperti putusan Majelis Ulama Jawa Barat yang membolehkan pemakaian spirla dengan alasan adanya dlarurat dalam bentuk ledakan penduduk. Padahal ledakan pen-duduk sama sekali bukan keaadan darurat, sebab darurat adalah “sesuatu yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan bahaya besar (halaka)”. Maksimal, manzilatadl-dlarurah”. Itu pun masih ada persoalan, yaitu apakah hajah demikian bisa beigtu saja menghalalkan melihat aurat besar ketika pemasangan spiral. Artinya ada batasan-batasan yang memperbolehkan keadaan hajah disamakan dengan keadaan dlarurah.
Oleh karena itu, A Azhar Basyir Ulama Muhammadiyah, mengusulkan sedikit perubahan pada kaidah tersebut menjadi al-hajah qadtanzilu manzilatadi dlarurah, hanya kadang-kadang saja setara denga dlarurah.
Jadi, pribumisasi adalah perlu, hanya saja masih ada persoalan ten-tang batas-batasnya.