Bahtsul Masail Membudayakan Berfikir Obyektif
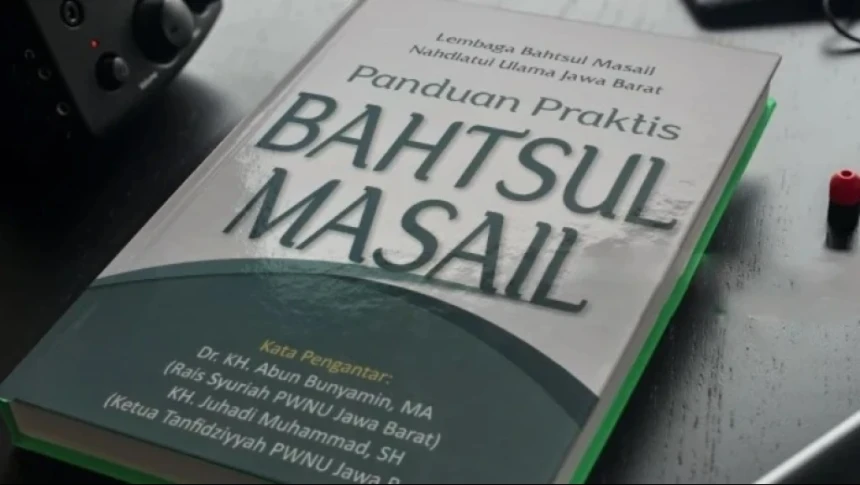
Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid
Beberapa catatan PBNU terhadap keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, 21-22 Muharam 1417, 8-9 Juni 1996, di PP Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Situbondo.
Di sini saya mendengar berberapa keputusan majlis bahsul masail yang memerlukan catatan-catatan dari PBNU Ini guna lebih memantapkan lagi majlis-majlis yang akan datang dalam kerangka bahsul masail.
Sebelum itu, secara guyon, menurut saya ada yang kurang lengkap. Mestinya kalau kawin secara komputer itu boleh dengan syarat, jima’nya juga harus secara komputer. Ternyata kita kurang komputer mainded. Komputer dihadapi dengan ahkam yang biasa saja, tentu saja tidak boleh. Karena itu, nanti perlu kiranya dipikirkan fiqhul komputer. Saat ini sudah ada fikih siyasi, tijari, dan fikih apa saja yang tidak ada sekarang ini.
Sebuah bahsul merupakan sebuah ukuran bagi kehidupan umat Islam dalam bentuknya yang berbeda-beda. Bahsul masail merupakan pembentuk sikap dan pandangan hidup umat. Dalam proses itu, bahsul masail berfungsi melakukan saringan-saringan yang memantulkan kewajaran dalam hidup kita sebagai umat Islam.
Inilah yang paling penting dalam sebuah bahsul masail. Rangkaian bahsul masail yang berstruktur dan berjenjang dari musyawarah di pondok-pondok, diangkat menjadi keputusan bahsul masail dari tingkat ranting, cabang, dan nanti bermuara ke Muktamar, merupakan sebuah proses berfikir dan proses mengukur ketepatan sebuah hukum.
Inilah yang membuat agama kita menjadi kuat, menjadi besar dan tetap dapat menjaga keutuhan umat. Karena dengan demikian lalu terjadi sebuah proses penserasian hidup dengan kenyataan-kenyataan yang ada terhadap cita-cita agama, terhadap kaidah-kaidah agama dengan tidak menghapuskan identitas agama itu sendiri.
Ini yang sudah tidak dimiliki oleh agama-agama yang ada sekarang di dunia ini. Karena pada umumnya, sudah melepaskan sisi legalistik, sisi hukum dari kehidupan mereka. Hanya Agama Islam yang masih melakukan hal itu, di samping agama Yahudi. Tetapi agama Yahudi pun mengalami krisis. Karena pedoman-pedoman hukum mereka tidak dikembangkan, melainkan ortodoksi atau kekunoan itu tetap tidak bisa menjangkau masa kini.
Umpama, pada orang-orang Yahudi di Israel sekarang timbul masalah. Satu misal, pada hari Sabat (Sabtu) mereka sama sekali tidak boleh kerja. Seorang yang mengendarai mobil apa dia bekerja. Apakah mengunci kontak mobil itu melakukan pekerjaan atau bukan.
Itu kan tidak relevan bagi kehidupan. Karena tidak relevan maka tidak diterima masyarakat umum. Mereka menjadi ekstrem, kalau ada mobil lewat pada hari Sabtu dilempari batu di beberapa daerah tertentu dari kota Yerusalem.
Ini satu contoh bahwa hukum mengalamai kesenjangan dengan kenyataan-kenyataan yang ada.
Sebaliknya dalam Islam, ada proses penyesuaian terus-menerus. Tadi baru disebutkan, menurut qaul qadim begini, menurut qaul jadid begitu. (Kata anak-anak mbeling, qaul qodim yang mengalahkan hanya qaul Kodam).
Jadi, ada rentang kelenturan spend of fleksibility. Kita boleh lentur. Yaitu dengan menetapkan syarat-syarat boleh tidaknya sesuat itu dilakukan. Syarat-syarat itu yang membuat lentur atau tidak.
Misalnya tadi. Dalam masalah rodat, boleh asal begini-begini. Itu artinya memakai syarat. Tidak dibebaskan begitu saja yang nanti lama-lama hadrah bisa menjadi ludruk. Tapi juga tidak dilarang karena itu ekspresi kejiwaan yang luhur. Orang yang melakukan lengkingan suara itu mungkin karena jazabnya atau apa begitu.
Spend of fleksibility, ruang bagi kelenturan, ini menjadi penting karena sekarang dalam kehidupan banyak pilihan-pilihan. Terhadap pilihan-pilihan inilah dijatuhkan hukum sampai di mana dia dibilang kelenturan dan sampai di mana itu keluar dari aturan agama.
Tadi disebut adanya talfik. Kita teringat yang pernah terjadi pada masalah perkawinan. Di situ diambil sepotong dari mazhab Maliki, sepotong dari mazhab Hanafi, pada akhirnya tidak karuan. Ini menjadi mazhab Malhan (Maliki dan Hanafi) atau mazhab Hamal (Hambali dan Maliki). Malah sebenarnya banyak ke Daud az-Zhahiri. Tapi masih bisa diartikan fiqhul mazahib.
Saya tidak mengerti itu. Kehidupan mazhab-mazhab sampai akhirnya menjadi empat yang muktabar itu kan sebenarnya mencerminkan enambelas mazhab yang besar dulu. Ternyata tidak mampu menjaga keseimbangan antara yang lentur dan yang tegas, dan antara yang lentur dan yang pasti. Kepastian dilenturkan dan kelenturan dipastikan. Ini yang membuat mazhab itu tidak bisa bertahan. Tinggal yang empat itu, karena di sana ada perangkat-perangkat yang memungkinkan adanya perkembangan yang lentur tadi tanpa kehilangan prnsipnya.
Contohnya almasholihul mursalah pada mazhab Maliki, al-ihtisan pada mazhab Hanafi, al-istiqra’ pada mazhab Syafii. Ini memungkinkan orang melakukan talfiq baina adillah al-naqliyah wa adillah al-‘aqliyah. Nah kita masih beruntung berbicara tidak hanya tentang kasus-kasus, tapi justru tentang mekanisme pembahasan, mekanisme pengambilan hukum. Pertanyaan dari cabang kabupaten Pasuruan tadi sangat bagus.
Yaitu mengenai fungsi hadis sahih dan masyhur yang mutawatir, yang dimaudlu’kan. Itu akan mendudukkan dengan jelas fungsi hadis. Walaupun sudah sering hadis harus tunduk juga kepada penafsiran. Tidak hanya lafalnya yang diambil tetapi penafsirannya. Dan di sini lagi-lagi terjadi ruang untuk kelenturan.
Saya rasa contoh klasik yang setiap hari kita dengarkan mengenai hadis tanakahu tanasalu taksuru fa’innı mubahın bikumul umam yaumal qiyamah…. Mubahin di sini dalam arti apa. Kualitatif atau kuantitatif. Ini ada keharusan untuk melakukan tafsil.
Saya merasa bergembira dapat menyaksikan dinamika perkembangan fikih di Indonesia melalui majlis bahsul masail yang kali ini diselenggarakan oleh PW NU jawa Timur di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Situbondo. Ini menunjukkan bahwa landasan berfikih kita masih kokoh, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri terhadap kebtuhan-kebutuhan zaman. Bahwa fikih kita adalah fikih yang maudhu’i, artinya obyektif sekali terhadap perkembangan hidup. Tidak ada unsur subyektifitas atau mau menangan sendiri di dalamnya.
Saya tadi guyon dengan Kiai Wahid Zaini, “Kiai, kok tidak kita dengar Mizanul Kubro li Sya’roni, sekarang dipakai untuk alasan kawin serampangan.” Alhamdulillah, tidak disebut-sebut Mizanul Kubro. Saya kawatir cara pemakaiannya serampangan. Tapi malah berkali-kali yang kita dengar kitab yang sudah baku. Seperti:
Majmu’, Syarkhu Muhazzab, Qalyubi wa Khumaira, al-I’anatut thalibin, Kifayatul Akhyar, Bughyatul Mustarsyidin. Memang itu senjatanya orang tukang geger. Tapi memang ampuh. Bahasa kerisnya Tosanaji. Alhamdulillah, itu semua terjadi.
Sisi lain dari adanya majlis bahsul masail dengan produk-produknya yang, kadang-kadang, tidak masuk akal. Yang saya ingat masih dalam tradisi lama, kisah di kitab fiqh yang menyebutkan min mubtilatil wudlu itu adalah menyentuh salah satu kedua kelamin. lalu in kanal mutawadhi’ dakholal farja qodruhu babun, wayalbas jauf, walam yalmas syai’an minhu — tidak menyentuh apa-apa sama sekali di dalam gua itu, apa batal wudlunya apa tidak.
Pertanyaannya bisa ditafsil: kalau umpama tangannya tidak memegang, kepalanya, kakinya tidak menyentuh, tapi menjilat bagaimana. Tambah tidak karuan. Jadi, sisi yang penting dari pembahasan-pembahasan itu adalah peluang yang diberikan kepada umat untuk membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya terhadap hadis innama umirtu an asjuda ‘ala sawadil a’zhomi. Yaitu, bathuk–kata orang Jawa. Pertanyaanya: in kanat jabhatani. Kalau ada orang mempunyai bathuk dua hal yakfi al-sujud bi ahadihima au bijuz’in minhuma ma’an. Ini juga bisa diteruskan bagaimana kalau ada orang sujud memakai helem.
Terhadap masalah yang tidak masuk akal tetapi aktual kita bisa berbicara, apalagi terhadap yang aktual yang menyangkut bangsa secara keseluruhan. Di sinilah tadi adanya pembahasan rancangan UUPA.
Nampak di sini, betapa hidupnya forum-forum semacam majlis bahsul masail dalam fungsi kontemporer. Fungsi yang haliyyan, masa kini. Karena dia menyangkut sendi-sendi keagamaan kita, maka itu diperlukan adanya kemampuan untuk membaca maksud dari rencana undang-undang dari ukuran-ukuran agama.
Alangkah bijaksananya bila rancangan itu dibawa ke bahsul masail sebelum dibawa ke forum lain di lingkungan jamiyah kita untuk akhirnya dilemparkan ke fraksi-fraksi di DPR. Ini menunjukkan adanya kemampuan NU untuk mengembangkan pranata-pranata di dalam dirinya yang sifatnya budaya agama, dalam arti dikerjakan setiap hari. Termasuk secara budaya: dibiasakan setiap hari memabahas, memikirkan serta memutuskan masalah seperti itu, kita turut menentukan arah dari perkembangan politik di negeri kita.
Ini yang sebetulnya mungkin kita kurang menyadari. Mungkin kita kurang memahami, bahwa fungsi bahsul masail itu bisa bersifat politis dalam jangka panjang melalui penataan budaya, pengarahan-pengarahan budaya melalalui ijtihad tsaqafiyah, membiasakan orang mengikuti hal-hal tertentu,
Kalau ini yang terjadi, maka Nahdlatul Ulama tetap berada pada posisi menemukan keseimbangan antara politis dengan yang tidak politis — yang budaya. Ini sangat penting, karena suatu bangsa apabila dia bersifat politis semata-mata, maka dia akan hanyut segala-galanya. Kehilangan segala-galanya demi kepentingan-kepentingan politis saja.
Kita lihat saja, nyatanya tambah lama negara ini — tiap negara dan negara manapun — cenderung mengagungkan kepemimpinan eksekutif. Cenderung sedemikian rupa, kita ini mengagungkan Pak Harto. Sampai-sampai urusan Bu Tien dianggap urusan bangsa. Wafatnya Bu Tien, seluruh bangsa ikut serta dalam proses.
Ini adalah bagian dari proses politik berupa pengagungan kekuasaan eksekutif. Kalau ini dihadapi secara politis pula maka akan terjadi konfrontasi. Akan terjadi suatu tarik-menarik dan dorong-mendorong untuk mengkensel, menetralisir satu sama lain. Kita lihat umpamanya, orang semacam Ali Sadikin, HR Darsono, Pak Nasution dan lain-lain yang dengan sengaja menentang arus memuliakan atau memenangkan eksekutif. Dengan segala risiko dan pengorbanan mereka. Dan kita tahu mereka kalah secara politis.
Tapi sebenarnya, kecenderungan politik demikian dapat dinetralisir melalui budaya. Dan itu sudah terjadi di NU. Juga dalam kasus wafatnya Bu Tien Suharto. Artinya, orang lain banyak menggunakan itu hanya untuk kepentingannya saja. Semua tahu, orang-orang itu tidak sungguh-sungguh. Ya dibuat-buat sedemikian rupa seperti yang paling tahu. Tidak pernah tahlil selama hidupnya, ikut tahlil. Mengambil oper dan memonopoli segala macam acara. Sementara yang NU tenang-tenang saja.
Artinya, kalau mau mendoakan memakai fatihah ya doakan biasa-biasa saja. Tidak usah macam-macam. Mau mendoakan tahlil ya tahlil dalam acara-acara yang umum seperti ini. Jadi merupakan kebiasaan yang wajar bukan sesuatu yang direkayasa sebagai hal yang mendadak timbul, lalu jadinya seperti begitu itu.
Di sini, budaya lebih menang dari pada politik. Karena apa? Karena politik tidak bisa memanipulir budaya. Orang NU tidak bisa dimanipulir oleh arus membesarkan kekuasaan eksekutif dengan lalu, orang NU ikut edan-edanan seperti yang lain-lain itu. NU tetap saja seperti biasa: membacakan fatihah ya membacakan fatihah.
Saya sendiri di depan Generasi Muda NU ya ikut membacakan fatihah. Tapi tidak perlu lapor Pak Harto sehabis membacakan itu. Sampai ada pertanyaan, kenapa sih NU tidak ikut-ikutan bikin apa-apa. Yang datang di Dalem Kalitan itu orang lain semua. Karena agak kepepet secara politis saya jawab, ya deh saya cek dulu. Kemudian saya cek ke Kiai Abdur Rozak Shofawi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad, Singoyudan, Surakarta.
- Bagaimana Kiai.
- Wong setiap malam di Kalitan kita yang mengirim santri.
- E, ya alhamdulillah.
Wong namanya budaya, tidak perlu resmi pengurus NU. Orang NU saja bisa. Tidak usah pakai baju NU. Kalau ada yang tanya bahwa NU kurang perhatian, kita jawab, tanya saja kepada mereka yang ke sana, NU atau bukan.
Pada hakikatnya keseluruhan dari acara wafat Bu Tien Soeharto memperlihatkan kemenangan budaya. Mengapa? Ternyata akhirnya keluarga Pak Harto mengambil proses budaya, yakni bertahlil. Kalau cara politisnya kan tidak perlu tahlilan. Sebab, sudah ada acara kebesaran, dukungan-dukungan pernyataan, sajak-sajak dibacakan segala, dan ada ini dan itu. Sudah cukup sesungguhnya.
Tapi ternyata, untuk beliau tidak cukup. Itu semua alat-alat politik yang tidak memuaskan batin dan rohani. Sebab tahu apa maksud di belakangnya. Tapi kalau tahlil itu barang yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa tahlil itu rekayasa. Tahlil tumbuh sendiri. Yaitu dari kebiasaan ulama terdahulu yang diteruskan ke masa sekarang. Sebab, tidak ada yang tahu siapa yang mengarang tahlil. Tahlilnya saja tidak sama.
Oleh karena itu, kita melihat dari situ. Pendekatan budaya lebih tepat digunakan dalam kehidupan bemegara dalam hal-hal yang tidak perlu dipolitikkan. Di sini letak pentingnya bahsul masail, karena di sini kita dengan tenang bisa membicarakan rancangan Peradilan Anak tanpa ada kepentingan politik sama sekali, tanpa ada kemungkinan dituduh mengacaukan jalannya sidang umum DPR. Tanpa ada kemungkinan dianggap sebagai kegiatan sparatis.
Kalau misalnya ingin protes bisa saja kita protes. Tapi kan ada tuduhan, kalau pemerintah yang membuat kok ada protes. Dia lupa bahwa yang bisa membuat undang-undang itu kan pemerintah. Kalau tidak kan petani Jenggawah bisa bikin surat sertifikat sendiri.
Nah di sinilah pentingnya arti bahsul masail bagi umat Islam dan juga bagi bangsa kita secara keseluruhan. Karena pendapat umat akan memberikan bekasnya sendiri bagi kehidupan kita. Seandainya RUU PA diundangkan begitu saja tanpa ada penyesuaian kehendak umat sebagaimana dihasilkan bahsul masail kita umpamanya, ya kita akan tahu, UU itu tidak kokoh, akan mengalami kemacetan-kemacetan dan akan mengalami tentangan-tentangan dari masyarakat.
Apalagi masyarakat sekarang sudah mulai sadar hukum. Mereka akan mengajukannya ke PTUN. Dan dı sana akan timbul masalah yang sangat besar: apakah undang-undang yang demikian itu dapat dipertanggungjawabkan menurut UUD 1945. Ini menyangkut masalah besar, karena kita sampai hari ini belum memiliki kewenangan membandingkan atau menetapkan kualitas undang-undang dilihat dari undang-undang dasar. Yang ada baru peraturan-peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, kaum Kong Hu Chu mengajukan gugatan kepada negara yang menetapkan Kong Hu Chu bukan agama. Lalu Kepres itu ditentang dan dihadapkan di pengadilan kepada undang-undang.
Sama saja kalau nanti UUPA tidak menyuarakan aspirasi umat Islam bisa saja kita ajukan sederetan gugagatan di pengadilan-pengadilan Tata Usaha Negara.
Inilah perlunya ada penyesuaian –dari pihak pengusul rancangan undang-undang — kepada pandangan keagamaan, supaya tidak terjadi kemacetan dalam sistem peradilan kita saking banayaknya perkara yang maju dalam hal yang dianggap cacat atau kurang.
Di sini tampak NU, alhamdulillah, mampu memelihara perangkat atau pranata dalam bentuk bahsul masail, yang akan menjadi pegangan warga negara, yang apabila RUU PA dipaksakan menjadi UU mereka bisa maju menuntut ke pengadilan. Dan memang hidup yang beradab bagi sebuah bangsa harus melalui Peradilan. Artinya ada kebebasan mutlak pengadilan untuk melakukan peninjaun terhadap peraturan-peraturan dan UU.
Jadi, yang kita lakukan dua hari di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo ini, bukanlah pekerjaan main-main. Tapi kita meletakkan batu bata bagi tembok bangunan hukum di negeri kita. Kelihatannya kita mengurusi perkara tetek bengek seperti orang terbangan itu, tetapi di balik itu ada masalah-masalah yang memerlukan peninjauan lebih mendalam lagi dari berbagai aspek karena dampaknya yang sangat jauh bagi kehidupan bangsa.
Padahal kita belum berbicara, apa hukum melepas tenaga nuklir atau energi dengan kurangnya persiapan-persiapan. Sehingga kemungkinan bencana bagi penduduk sekitar menjadi sangat besar. Ini urusan PLTN Muria yang seharusnya dibahsul masailkan. Tapi, kita belum bisa karena tidak punya peralatan informasi dan data-data untuk melakukan hal itu dengan baik dan tepat.
Tapi kita harus berfikir, NU mengembangkan pranata bahsul masail di masa yang akan datang secara lebih canggih. Artinya masalah-masalah yang dibahas memiliki kecanggihan tersendiri. Seperti yang saya katakan tadi tentang tenaga nuklir.
Tadi ada pertanyaan yang sangat baik tentang AIDS. Sangat menyentuh secara kemanusiaan, tapi juga sangat praktis dari sudut kesehatan. Ini merupakan suatu hal yang –bagi saya– sangat berarti di tengah-tengah merosotnya pemikiran keagamaan yang ada sekarang. Sebab, pemikiran keagamaan sekarang hanya di arahkan untuk membenarkan langkah-langkah pemerintah. Memberikan validitas, shihiyyah kepada program pembangunan pemerintah. Itu pun seharusnya disertai dengan kemampuan untuk membahas secara mendalam dampak-dampak jangka panjang, sehinga shihiyyah itu tidak mutlak harus ditundukkan kepada persyaratan-persyaratan. Mustinya seperti tadi: boleh asal… (ada catatannya).
Walaupun kadang-kdang kita bingun dengan bahasa fikih seperti “boleh tapi makruh.” Makruh ya makruh, kok boleh. Makruh itu barang yang tidak boleh. Kita kok menyampur-campurkan. Hukum fikih itu kan ada lima. Wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Boleh itu kan jawaz. Yajuzu walakin yukrahu kan belum pernah dengar.
Suatu hal yang harus kita lihat secara mendalam, kita batidakan secara tepat. Ini bagian dari al-takabbur ‘ala mutakabur shadaqah. NU ini kan dicaci maki tidak karuan. Termasuk dibilang kolot, tradisional, statis, goblok, dan seterusnya. Semua itu jawab kita tunjukkan bahwa, “aku punya bahsul masail, sedangkan kamu apa kata bapak ketua.”
Dengan demikian tampak, bahwa kekayaan budaya (tsurwah tsaqafiyah?) yang dimiliki jamiyyah NU sangatlah kaya, sangatlah besar. Dan, ini yang membuat NU besar. Bukan karena politiknya.
Kalau politiknya, sebetulnya NU sudah runyam sejak dulu, kalau tidak ada tsaqafahnya itu. Sebab politik kita tidak pernah rukun. Ada yang berpandangan A, B, C begitu rupa dalam politik, tapi toh masih bisa satu jamaah dan satu jamiyyah. Itu kan karena tsurwah tsaqafiyahnya, kekayaan atau warisan budayanya. Yang di PPP dan Golkar itu jelas sama gegernya, tapi mereka tunduk pada fikih yang sama. Dan itu yang membuat mereka jadi NU dan rukun. Rame, hanya kalau menjelang pemilu. Selebihnya besan-besanan. Begitulah NU.
Maka kekayaan budaya ini seharusnya kita pakai lebih tajam untuk mengoperasi hal-hal yang tidak wajar yang terjadi dalam kehidupan bangsa kita secara budaya, bukan operasi politik. Mana yang perlu disayat dan dibuang, dan mana yang perlu diteruskan atau dipelihara. Kebudayaan untuk mengatakan yang ada itu begini ya begini. Karena katanya fikih itu begini, katanya kitab-kitab itu begini, ya begini — tidak bisa lain.
Ini artinya kita memotong budaya asal bapak senang (ABS). Sebetulnya kan ke situ larinya. Dan ini sangat penting. Sebuah bangsa yang hidupnya ABS — atasan senang, mertua senang, orang tua senang, guru senang — ini adalah bangsa tempe yang tidak akan mencapai prestasi apa-apa.
Ketika semua orang ada komando bahwa kapal terbang kita ini hebat semisal Gatotkoco. Kata orang yang mbeling-mbeling, itu singkatan dari Gagal Total Kakehan Cocot, Yang lain bilang, N-250 itu: angka dua untuk tanda mesinnya, angka lima tanda krunya (pilot, co pilot, dan tiga kru) dan angka nol itu penumpangnya. Tidak ada yang berani naik.
Cerita mbeling lain: Kapal itu dibawa perang ke Bosnia. F-16 dibedil dengan meriam udara, tidak kena saking cepatnya. Air Was dan macam kapal-kapal lain seperti Mirage ditembak dari bawah. Waktu N-250 lewat dibiarkan saja. Panglimanya tidak memerintah komandan pengawal meriam itu untuk menembak. Anak buahnya bertanya kenapa ini kok tidak ditembak: Biarkan saja nanti kan jatuh sendiri. Tidak ditakuti orang sama sekali.
Berdasarkan budaya ABS, maka tidak ada orang yang bertanya cocok-tidak antara ongkosnya dengan harga jualnya. Tahu-tahu mendengar berita mau dijual ditukar ketan. Lha sekarang anak-anak di Jakarta yang senangannya makan ketan hitam itu kalau ada batu tercampur di dalamnya tergigit: Ehh… ada pesawatnya.
Lho saya membanyol ini menunjukkan ketidak wajaran satu proses, yang harus menerima mentah-mentah tanpa dijawab berfikir. Dianggap yang boleh mikir pesawat hanya ahli pesawat. Padahal pemakainya juga boleh mikir dong. Yang boleh memikirkan pembangkit tenaga nuklir hanya ahli atom. Lho orang awam ya boleh mikir dong, sebab kalau ada apa-apa yang mati orang awam kok. Sang ahli berada di tempat jauh, slamet-slamet saja.
Ini contoh bahwa kita harus menegakkan ukuran-ukuran yang sehat dan obyektif dalam jangka panjang. Bukan ukuran-ukuran asal bapak senang.
Bahsul masail ini, walaupun tidak pernah membicarakan pesawat terbang N-250 dan pesawat sebelumnya CN-235 yang namanya Tetuko-kata yang mbeling singkatan “sing teko ora tuku, sing tuku ora teko-teko” — ukuran obyektif perlu ditegakkan.
Walaupun bahsul masail tidak menyebut soal itu karena peswat terbang itu tidak masuk lingkup fikih kecuali kalau digunakan secara salah. Pesawatnya sendiri itu kan di luar hukum. Tetapi kebiasaan kita melihat sesuatu secara obyektif, secara maudhu’i, tidak secara karena senang saja, sikap hidup yang dikembangkan melalui proses bahsul masail ini, adalah sumbangan NU yang sangat berharga bagi pertumbuhan budaya politik yang sehat di kemudian hari dalam kehidupan bangsa kita.
Ini yang harus kita syukuri. Karena kita itu, kita juga harus memeliharanya dengan baik. Termasuk di dalamnya, kita melangsungkan bahsul masail ini dengan penuh kejujuran. Tidak main-main. Dengan kesungguhan tidak dengan enteng-entengan saja.
Sekarang sudah banyak orang memberikan fatwa enteng-entengan saja. Seperti fatwa MUI dulu di tingkat pusat (waktu saya juga masih dalam MUI). Saya gegeri, karena mereka mengatakan makan kodok haram, tapi membudidayakannya halal. Saya bilang, kalau begitu mucikari yang tidak ikut jima’ pelacurnya itu ya halal dong. Dia hanya membudidaya kan. Kalau diambil qiyasnya kan begitu.
Itu karena niatnya sudah tidak benar. Yakni supaya mendapat persenan dari pengusaha pemelihara kodok. Seperti membuat hukum SDSB, saya tahu persis. Waktu itu saya salah satu ketua MUI. Jawaban MUI sangat tidak jelas (mubham): Kalau ini permainan maka halal. Padahal barangnya sudah jelas, kok “kalau.”
Saya bilang: Kiai, kitab fikih itu ada dua macam: Satu, yang membawa masalah dan diselesaikan dengan jenis kitab Bughyatul Mustarsyidin dan lainnya. Kedua, ada yang masalahnya ditambahi “lau,” belum dijawab sudah dilau lagi. Seperti kitab Tahrir. Anda itu model Tahrir bukan model Bughyah. Kemudian mereka bertanya, Takhrir itu apa. La ilaha illallah. Begini saja tidak tahu kok berani ikut fatwa.
Itu artinya, kita main-main dengan fatwa. Main-main dengan bahsul masail. Sedangkan di NU dimulai dengan titik tolak yang sangat hati-hati. Belum pernah kita mengatakan hasil yang kita buat ini sebagai fatwa. Ini adalah hasil bahsul masail. Untuk tingkat ifta’ itu ada sendiri yang memutuskan. Tidak bisa setiap forum.
Karena itu, marilah kita pelihara perangkat bahsul masail ini dengan sebaik-baiknya.