NU, Muhammadiyah, dan Pancasila
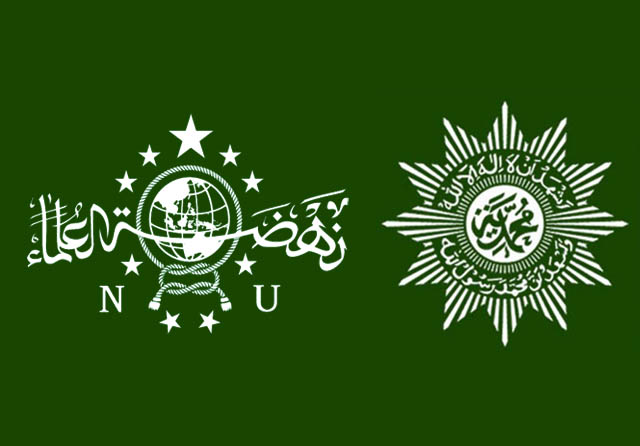
Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid
Pancasila akhirnya diakui sebagai dasar negara kita. Yang berbeda atasnya adalah penafsiran yang dilakukan orang. Walaupun kata Pancasila itu sendiri dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi di luar penafsiran itu sikap yang diambil bangsa kita sesuai sepenuhnya dengan Pancasila. Pada tahun 80-an, Pancasila secara resmi ditafsirkan oleh Pak Harto dan para anak buahnya sebagai ideologi yang membenarkan kekuasaan. Dalam penolakan mereka atas hal itu, kemudian banyak yang mengganti Pancasila dengan istilah-istilah lain. Hal ini dilakukan oleh orang-orang luar negeri maupun pihak-pihak dalam negeri yang bergantung untuk tetap dapat hidup kepada mereka. Karena UUD 1945 tidak mencantumkan otonomi daerah maupun secara eksplisit menolak sentralisme yang begitu pokok menguasai sistem politik kita, maka muncullah usul untuk melakukan amademen atas UUD tersebut.
Prof. Dr. Amien Rais, sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mengikuti saja keinginan itu seperti tanpa ingat bahwa diperlukan ketelitian dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi. Ketidaktelitian itu tampak dalam kenyataan bahwa ketetapan MPR-RI yang menetapkan UUD 1945 adalah instrumen dasar negara, tidak dibuat ketetapan menghapuskannya. Demikian pula, UUD pengganti (sebut saja UUD Perubahan tahun 2002) tidak pernah dimusyawarahkan secara luas dalam waktu yang cukup lama.
Di samping itu, UUD Perubahan tidak diundangkan sebelum ia diumumkan sebagai UUD baru, serta belum pernah masuk dalam lembaran negara. Padahal MPR-RI telah menetapkan bahwa sejak tahun 2002, lembaga itu tidak akan mengeluarkan ketetapan lagi. Dengan demikian, menjadi pertanyaan apakah UUD Perubahan dapat dipakai sebagai instrumen negara atau tidak? Dalam hal ini, pikiran sehat menyatakan bahwa kita sebenarnya masih memiliki UUD 1945 sebagai instrumen dasar negara kita. Tetapi pertimbangan politik pada akhirnya memaksa sejumlah parpol maupun pihak eksplisit pemerintahan untuk tetap menggunakan UUD Perubahan itu.
Padahal perubahan UUD bagi sebuah negara adalah masalah prinsipil, yang harus diputuskan tanpa ada keraguan sedikitpun. Penafsiran atasnya-pun harus selalu dilakukan, untuk menghindarkan penafsiran “diam-diam” yang dapat saja dilakukan atasnya selama kita lalai dan tidak menjaganya dengan teliti. UUD Amerika Serikat sudah berumur 200 tahun. Tetapi perdebatan berkepanjangan antara Presiden ke-3 Thomas Jefferson dan menteri keuangan Alexander Hamilton sampai sekarang masih saja berjalan. Jefferson lebih mementingkan penjagaan hak-hak individu, yang sekarang berjalan begitu jauh, hingga negara menyukai perkawainan kaum gay (kaum homoseksual) sebagai ikatan yang sah dan mempunyai akibat-akibatnya sendiri. Sebaliknya pendapat Hamilton mengenai pengutamaan hak-hak Negara Bagian sebagai kolektivitas terkecil dalam negara melahirkan kekuatan-kekuatan politik seperti George Bush, Richard Nixon dan Ronald Reagan. Kedua kekuatan itu berada dalam pemilihan umum presiden.
Terus terang saja, sekarang ini, gerakan Islam sedang mengalami perkembangan luar biasa di negeri kita. Ini tampak terutama dalam munculnya berbagai macam kegiatan di kalangan kaum muslimin, yang tidak seluruhnya termasuk warga berbagai organisasi keagamaan Islam. Banyak di antara mereka yang memunculkan “semangat ke-Islaman” dalam berbagai kegiatan mereka. Umpamanya saja kegiatan kampus, karang taruna, dan remaja masjid. Maka lahirlah berbagai “gerakan Islam” yang dipakai untuk tujuan politik, seperti halnya pemanfaatan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dewasa ini memiliki dampak politiknya sendiri. Menjadi pertanyaan besar bagaimana gambaran “kekuatan politik Islam” dalam pemilu tahun 2009 nanti. Masihkah berakibat pada NU dan Muhammadiyah?
Untuk meninjau secara tepat kemungkinan-kemungkinan bagi gerakan Islam di masa depan ini, patutlah ditinjau hubungan politik antara NU dan Muhammadiyah di satu pihak dan Pancasila di pihak lain. Karena sebagai gerakan Islam terbesar di negeri ini, NU dan Muhammadiyah dahulu mempelopori penerimaan Pancasila. Bahkan ketika banyak anggota Muhammadiyah menjadi pimpinan partai Islam terbesar Masyumi, Muhammadiyah sebagai organisasi tidak pernah menyatakan penentangannya terhadap “ideologi negara” Pancasila KH. A. Wahid Hasyim dari NU mendukung temuan Soekarno akan Pancasila dalam tahun 1945. Ia kemudian bekerja sama dengan saudaranya, KH. A. Kahar Muzakkir dari PP. Muhammadiyah. Beliaulah yang kemudian mengusulkan pada rapat yang dipimpin oleh Moh. Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945, agar menerima Pancasila. Dengan demikian terjadi dua hal sekaligus: penolakan gagasan negara Islam dan penerimaan Pancasila.
Hal-hal seperti inilah yang seharusnya kita perdebatkan, untuk memperkaya misi dan visi kita dalam hidup bernegara. Di kalangan organisasi-organisasi Islam, hal itu telah terjadi secara sangat merugikan. Bagi yang tetap menginginkan negara Islam, tidak banyak argumentasi yang dapat dikemukakan untuk memperkuat tuntutan mereka akan sebuah negara. Bagi pihak yang menerima Pancasila dan menolak adanya negara Islam, tidak dirasakan dan diketahui bahwa perjuangan berat itu telah dilakukan baik oleh NU maupun Muhammadiyah. Keterhentian informasi menyebabkan dialog yang tuntas dan hidup dapat dilakukan bagi kepentingan negara dan bangsa. Yang ada adalah kecurigaan yang membabi buta antara dua macam tuntutan itu. Karena itu, masalah tersebut harus dibangkitkan dan diperdebatkan oleh kalangan yang luas. Bukankah kita perlu dialog yang matang akan konstitusi kita sendiri?