Antara NKRI dan Federalisme
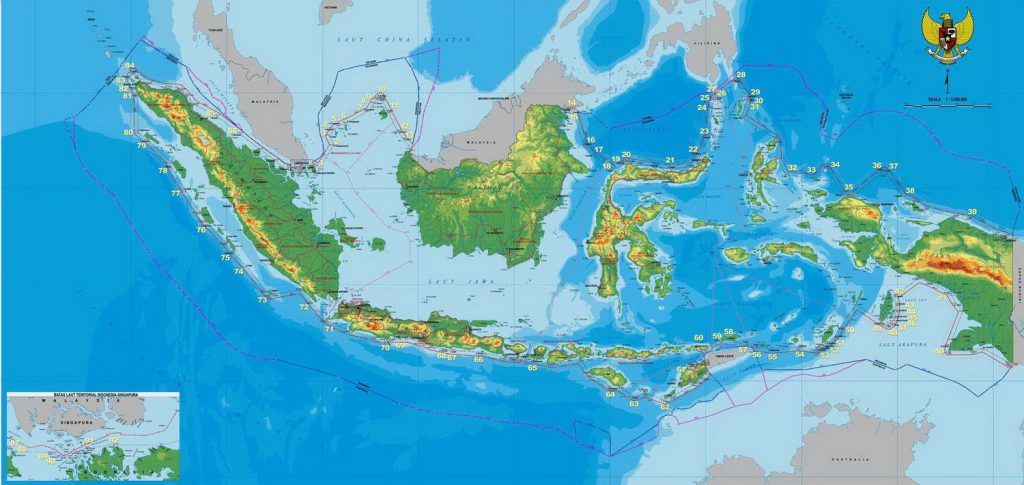
Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid
Istilah NKRI dipakai oleh para pendiri negara ini untuk menunjukkan bahwa ia adalah sebuah negara dengan kepemimpinan tunggal dan arah perjalanan hidup yang sama bagi warga bangsa ini.
Istilah tersebut, yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijadikan lawan bagi sebuah istilah lain, yaitu keberbagaian (pluralitas) dan toleransi. Ini semua perlu diadakan untuk menjawab tantangan bahwa kita tidak mungkin membuat sebuah negara dan bangsa yang bersatu. Apalagi kita memang hanya memiliki sedikit pengacara yang berkemampuan, beberapa bidang telah memiliki format-format yang jelas sehingga tidak memerlukan penegasan. Contohnya adalah bahasa nasional kita yang dikembangkan dari bahasa Riau, antara lain oleh Raja Haji Ali, yang dimakamkan di Pulau Penyengat.
Dari bahasa Riau itu, kemudian muncul dua buah bahasa pada tingkat nasional, yaitu bahasa nasional kita (dikenal dengan nama bahasa Indonesia). Sedangkan ia juga dijadikan bahasa nasional Malaysia (disebut juga bahasa Malaysia). Untuk mendukung keberadaan bahasa Indonesia itu, dibuatlah istilah NKRI. Tentu saja, hal-hal seperti itu tidak pernah dijelaskan dengan gamblang. Kejelasan itu akan diperoleh dari penggunaan istilah NKRI itu dan dari perkembangan bangsa dan negara sendiri.
Karena kedua-duanya ternyata berkembang dengan baik, maka semakin lama istilah itu semakin sedikit. Lalu timbul keinginan untuk menekankan kesatuan. Karena adanya tuntutan lain, maka dengan sendirinya istilah NKRI semakin banyak muncul dalam pembicaraan di kalangan bangsa kita. Sebabnya, banyaknya tuntutan akan semakin memupus kekuatan pusat (dan tentu saja semakin kuatnya kekuatan pemerintah daerah dan penambahan kekuasaannya), serta bertambah meningkatnya tuntutan otonomi daerah, ada pihak yang merasa bahwa kedua hal itu tidak perlu dikemukakan lagi, minimal dalam rumusan resmi berbagai instrumen dasar negara kita. Dengan sendirinya, hal itu akan diliput oleh berbagai undang-undang organik.
Dengan demikian, instrumen-instrumen dasar tersebut tidak perlu kita ubah dan tidak perlu adanya amendemen. Dengan demikian, pola dialog tentang UUD menjadi “kemasukan angin” dan kita lalu berdialog dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Sebenarnya, kerancuan dialog inilah yang harus kita mengerti, bukannya “salah sambung” yang terjadi antara kita sendiri. Memang, mencari pengertian yang sama tentang sesuatu hal, apalagi yang terkait dengan instrumen dasar sebuah negara, bukanlah pekerjaan mudah. Ia memerlukan juga kejujuran mutlak di samping kemampuan (expertise).
Karena itu, dialog di antara berbagai pihak tentang instrumen dasar negara seperti digambarkan di atas memerlukan kesabaran dan jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, cara “menyelesaikan” masalah undang-undang dasar kita memerlukan ketabahan yang boleh di kata luar biasa. Karena itu, panjangnya waktu dan penunjukan siapa yang membicarakan undang-undang dasar itu, menjadi sangat penting bagi negara kita. Penilaian akhir tentang perlu atau tidaknya UUD kita di amendemen, bukanlah perkara kecil. Dalam sebuah halaqoh tentang konstitusi dan temu wicara hukum acara yang diselenggarakan DPP PKB dan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, penulis menyatakan bahwa penulis adalah korban dari sebuah komplotan jahat yang akhirnya memaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI pada 21 Juli 2001.
Mengapa penulis menamakan proses itu sebagai komplotan, berarti ada sesuatu yang melanggar hukum dan menentang konstitusi? Jawabnya karena hal itu memang demikian, dimulai dari Pansus Bulog dan Brunei Gate, yang dipimpin oleh Bachtiar Chamsyah. Hal itu saja sudah dapat menunjukkan proses idealisasi yang menganggap nilai-nilai yang dianggap “islami” sebagai capaian yang harus diperoleh organisasi-organisasi Islam. Bukankah itu pelanggaran konstitusi? Bachtiar Chamsyah sendiri melakukan pelanggaran undang-undang dengan membiarkan pintu sidang-sidang pansus terbuka sekitar sepuluh sentimeter. Maksudnya, agar para wartawan dapat merekam pembicaraan yang terjadi dalam ruangan.
Padahal, sebuah undang-undang secara spesifik melarang sidang-sidang pansus dilakukan secara terbuka. Memang, karena dari semula sejumlah parpol dan perwira tinggi TNI sudah memutuskan untuk menyingkirkan penulis dari jabatan Presiden RI. Karena itu, segala macam pelanggaran dibiarkan saja. Bahkan, alasan formal yang tadinya berupa “pelanggaran legalitas”, akhirnya tidak dapat dibuktikan. Akibatnya, diambil keputusan politik untuk menyingkirkan penulis dari jabatan kepresidenan. Ini dengan berbagai macam pelanggaran seperti tidak adanya pembicaraan hal itu di DPR RI dan pelanggaran di Mahkamah Agung, ketika keputusannya diberitahukan kepada MPR RI oleh ketua Mahkamah Agung RI.
Padahal, undang-undang menyatakan bahwa hal itu harus diputuskan dan disampaikan oleh sebuah komisi khusus di lingkungan MA sendiri. Penulis bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut, hanya karena ia tidak menyukai perang saudara antara sesama warga negara RI, yang tentu akan menimbulkan korban jiwa. Nah, soal pribadi seperti itu ternyata membawakan dominasinya sendiri sehingga soal-soal yang berkaitan dengan kondisi hukum nasional kita terabaikan sama sekali dan tidak dibicarakan lagi.
Tentu saja, di antara hal yang harus dibicarakan dalam masalah pelanggaran terhadap konstitusi yang terjadi semakin banyak akibat dari sikap ini adalah merajalelanya korupsi di hampir semua bidang kehidupan. Baik oleh warga negara di luar pemerintahan, juga oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti kemalasan para birokrat kita untuk mendasarkan perbuatan mereka kepada kemampuan lembaga-lembaga pemerintahan sendiri. Kaum birokrasi pemerintahan yang mana pun akan membawa cara kerja mereka sendiri dalam menentukan sikap. Dengan langkanya penerbitan atas cara kerja para pegawai negeri yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang itu sendiri menjadi sebuah sikap yang mati-matian dipertahankan. Herankah kita kalau hal seperti itu membawa kepada pendapat bahwa korupsi tidak bisa hilang dari negeri kita?