Membangun Kembali Tradisi Keilmuan Islam (Kata Pengantar)
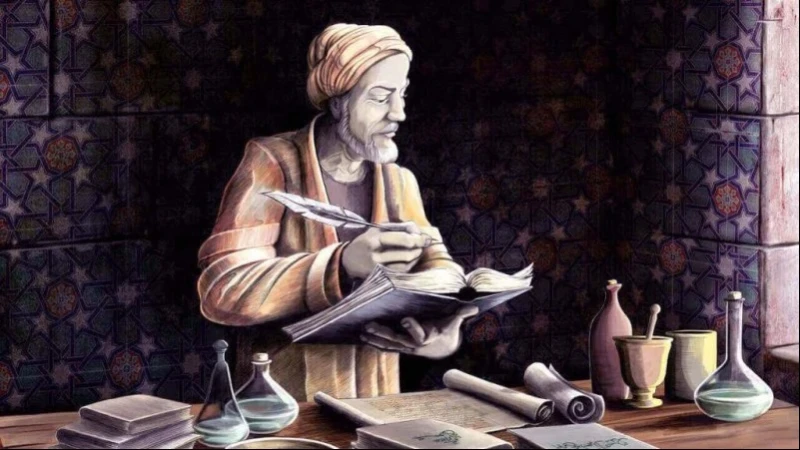
Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid
Bahwa Islam memiliki tradisi yang kuat di bidang ilmu pengetahuan di masa lampau, bukanlah pernyataan yang terdengar aneh. Kesaksian sejarah telah diberikan untuk itu, dengan munculnya begitu banyak ilmuwan dan penemu yang berasal dari peradaban Islam. Bahkan cukup banyak sejarawan ilmu (science historians) yang menyebut peradaban Islam di zaman keemasannya sebagai “Peradaban Ilmu”. Tidak ada bidang ilmu pengetahuan dikenal di waktu itu yang tidak memiliki pemuka-pemuka dari kalangan kaum muslimin. Bahkan banyak cabang dan bidang baru dalam ilmu pengetahuan, yang dirintis dan diciptakan oleh para sarjana muslim, seperti Aljabar. Demikian pula, beberapa cabang yang di kemudian harinya dinamai ilmu pengetahuan modern, sebenarnya telah dirintis oleh para ilmuwan muslim, seperti Sosiologi dan Filsafat Sejarah (Philosophy of History) yang dirintis oleh Ibn Khaldun.
Aspek lain dari kebesaran Islam di bidang ilmu pengetahuan di masa lampau itu adalah sumbangan peradaban Islam kepada kebangunan pengetahuan dan peradaban Barat di kemudian hari. Dainel Defoe jelas sekali terpengaruh oleh Hayy Ibn Yaqzan-nya Ibn Tufail, di kala menulis karya utamanya, Robinson Croesoe. Goethe, yang merupakan puncak dunia puisi Jerman hingga saat ini, mengambil banyak sekali dari karya-karya puisi kaum Sufi. Jean-Jacques Rousseau memasukkan unsur-unsur teori pemerintahan yang dikembangkan para sarjana hukum muslim untuk karya utamanya, Le Contract Social. Hingga hari ini pun, masih juga terasa besarnya sumbangan para pemikir muslim bagi beberapa ilmu pengetahuan, seperti filsafat dan teori ilmu pengetahuan.
Peradaban Islam dari masa lampau, melalui pengolahan kembali, masih mungkin memberikan sumbangan sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang konon sudah tidak memungkinkan “perkembangan sektoral” ini, ketika sistem komunikasi dan dokumentasi ilmiah sudah begitu menyatukan dunia dan tidak mungkin dikenal bagi sumber dan asal-usul informasi yang dikembangkan umat manusia. Apa yang diperbuat oleh Ali Shari’ati di Iran sebelum era Khomeini adalah sebuah contoh dalam hal ini. Juga rintisan Abdul Hamid Al-Zeyyin di bidang Antropologi. Sejumlah rintisan di bidang ilmu ekonomi jelas menunjukkan secara ilmiah keburukan fatal dari sistem kapitalisme Internasional, yang pada waktunya nanti akan merupakan sumbangan amat berharga bagi penyusunan ilmu ekonomi yang baru, yang bebas dari keharusan “paradigma sistemik” nya dewasa ini. Bagaimana menyusun ekonomi bebas-riba, bagaimana membuat keseimbangan antara produktifitas tenaga kerja dan pemerataan hasil kerja dan sebagainya, termasuk masalah-masalah yang secara teoritis sedang digumuli para ekonom muslim di mana-mana. Kita boleh bersengketa tentang kelayakan kerangka yang mereka gunakan, yaitu menciptakan sebuah teori Ekonomi Islam, namun kerja yang mereka lakukan itu niscaya memberikan sumbangan besar kepada Ilmu Ekonomi di kemudian hari.
Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa peranan Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan terus menurun secara drastis sejak berakhirnya zaman keemasan peradaban Islam. Kaum muslimin bukan hanya kehilangan posisi memimpin yang dipegang selama berabad-abad di dunia ilmu pengetahuan, mereka justru dihina martabat mereka dan dijajah oleh bangsa-bangsa yang melanjutkan tradisi keilmuan mereka. Dengan kata lain, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemandekan total di tangan mereka, dan diambil alih oleh bangsa-bangsa lain yang menjajah mereka. Bahkan lebih jauh lagi, sendi-sendi keimanan banyak manusia muslim mengalami krisis dan bahkan kehancuran, di hadapan tantangan yang dibawakan oleh ilmu pengetahuan modern. Kapitalisme Internasional, sebagai sebuah sistem ekonomi yang menguasai kehidupan umat manusia saat ini, telah membawakan skala prioritasnya sendiri ke dalam tatanan kehidupan hampir semua negara-negara dengan jumlah penduduk beragama Islam cukup besar (termasuk merupakan minoritas, seperti India dan Sri Lanka), skala prioritas itu umumnya dinamai “program pembangunan nasional”, yang nyata-nyata menunjukkan watak materialistik dan dengan sendirinya merupakan dehumanisasi kehidupan, karena menempatkan manusia hanya sebagai obyek kerja manipulatif untuk menjajakan hasil-hasil produksi konsumtif belaka. Orientasi “pembangunan” seperti itu, dengan sendirinya akan merupakan antitesa dari pandangan Islam yang menyatakan keseimbangan dalam kehidupan individual maupun sosial manusia.
Untuk mampu melepaskan diri dari jeratan dominasi materialisme dalam kehidupan manusia, yang akan membawakan dehumanisasi total kehidupan itu sendiri, bangsa-bangsa Muslim (dan sudah tentu juga bangsa-bangsa bukan muslim) harus menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk menyusun “agenda pembangunan” yang baru, yang akan merupakan rintisan bagi penciptaan peradaban baru umat manusia di masa depan. Prioritas pengembangan diri mereka harus disusun kembali skalanya, dalam pola dialogis yang kreatif dengan salah satu unsur dari sistem kapitalisme Internasiol, yaitu apa yang disebut sebagai “proses modernisasi”. Dengan ungkapan lain, kaum muslimin harus merumuskan modernisasi yang bercorak sesuai yang mereka ingini. Dalam upaya tersebut, mau tidak mau haruslah dilakukan tinjauan mendalam atas tradisi keilmuan yang telah dikembangkan dan dimiliki oleh Islam dalam sejarahnya yang berkembang sejak empat belas abad itu.
Untuk mengenal tradisi itu, beberapa hal harus lebih dahulu diketahui, yaitu yang dimasukkan dalam pokok-pokok berikut: (a) asal-asul tradisi keilmuan itu sendiri; (b) watak utama yang dimilikinya; (c) kekuatan yang melestarikannya; (d) peranan dalam mengarahkan kehidupan kaum muslimin;.
Dari pengenalan hal-hal itu, sosok tradisi keilmuan dalam Islam akan muncul sebagai sebuah kekuatan yang akan memungkinkan kaum muslimin masa kini untuk menyusun “agenda kerja ilmiah” mereka sendiri; sedangkan agenda tersebut akan menentukan skala prioritas kerja pembangunan yang diperlukan dalam mencapai modernisasi yang mereka inginkan.
Sumber Tradisi Keilmuan Islam
Tradisi keilmuan dalam Islam bermula dari kedua sumber utama keimanan manusia muslim, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulillah. Kedua sumber itu merupakan sekaligus batasan bagi ruang gerak para ilmuwan muslim dan obyek penalaran mereka. Ruang gerak mereka dibatasi oleh ketentuan, bahwa mereka tidak diperkenankan untuk memikirkan zat Tuhan dan hakikat-Nya, serta tidak dibolehkan mengembangkan “pengetahuan” yang membawa kerusakan bagi umat manusia. Pembatasan tersebut berarti orientasi ilmiah para ilmuan muslim haruslah bersifat manusiawi dalam arti yang luas, dan memiliki dimensi moral yang kuat dalam dirinya.
Al-Qur’an dan Sunnah menjadi obyek penalaran, karena sejak semula para ilmuwan muslim harus menangani penghadapan kedua sumber utama keimanan mereka itu kepada wawasan ilmu pengetahuan serba kosmopolitan dari Hellenisme yang berkembang di Timur Tengah di saat kelahiran dan perkembangan mula-mula Islam. Campuraduknya pemikiran ilmiah, terutama bidang filsafat, antara filsafat Kristen awal, filsafat Yahudi dan sisa-sisa filsafat Yunani (termasuk Okultisme dari Neo-Platonisme) serta berbagai ajaran filsafat dari Timur (Macheianisme dan sebagainya), akhirnya memaksa para pemikir muslim pada permulaan abad kedua Hijri, untuk melakukan penalaran mendalam atas kategorisasi-kategorisasi ilmiah yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
Penalaran pada tingkat dini itu menghasilkan sejumlah disiplin ilmu dalam Islam, yaitu ilmu Riwayah (otentifikasi transmisi kedua sumber utama itu) dan Ilmu Bahasa. Dari ilmu Riwayah akan lahir ilmu-ilmu Hadis dengan segala cabang-cabangnya serta ilmu-ilmu Al-Qur’an dalam abad-abad berikutnya. Sisi tersebut dapat dimasukkan jenis-jenis ilmu yang mengembangkan aspek formal dan normatif dari Islam, dan akan berujung pada hukum Islam.
Sebaliknya, Ilmu Bahasa sejak semula telah memperlihatkan watak yang eklektik: masukan begitu banyak dari berbagai peradaban diserap tanpa kehilangan identitasnya semula, dalam sebuah ikatan integratif yang longgar. Dari Filsafat Yunani dipinjam pembagian “ilmu-ilmu yang sepuluh” (Fisika, Metafisika, Etika dan seterusnya), di samping kategorisasi peristilahan ilmu. Hal itu tentu sebagai akibat dari ketentuan logika yang dipinjam dari filsafat Yunani. Dari peradaban Romawi dipinjam tata organisasi dan administrasi pemerintahan, yang tentunya harus dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan tertulis yang disebut ilmu pemerintahan. Dari agama Yahudi dan sekte-sekte bidat Kristen dipinjam peristilahan yang berhubungan dengan Gnosis (dalam bahasa Arab disebut Ma’rifah). Dari peradaban Persia (dan Asia Tengah pada umumnya) diserap pengetahuan tentang musik, kritik sastra dan unsur-unsur arsitektur non-Hellenistik.
Dari penyerapan yang begitu ekstensif dan kemampuan meletakkannya dalam kerangka yang tidak saling tolak menolak itu, akhirnya tersusunlah pengetahuan sangat luas, yang memerlukan pembakuan Bahasa Arab dalam rangkaian karya-karya dasar seperti kamus umum, kamus peristilahan, ensiklopedia dan sebagainya. Kamus tertua, yaitu Qamus al-‘Ain yang disusun Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, ditulis masih dalam paroh pertama abad kedua Hijri, sedangkan buku standar tata bahasa Arab (berjudul Kitab) ditulis oleh muridnya, Sibawaih, masih dalam paroh kedua abad yang sama. Ensiklopedia pertama, kitab Al-Ma’arif, ditulis oleh Ibn Qutaibah Al-Dinawari dalam perempat abad pertama abad ketiga Hijri, bersamaan dengan buku standar sejarah Rasul berjudul Maghazi Rasulillah dari Al-Waqidi, Sirah Nabawiyah oleh Ibn Hisyam, Tabaqat karya Ibn Sa’d (11 jilid) dan Al-Muwaffaqiyat karya Bakar Ibn Zubair.
Dari karya-karya yang membakukan pengetahuan dan bahasa itulah kemudian muncul dalam abad-abad berikutnya karya-karya utama seperti Kitab Al-Hayawan dari Al-Jahiz, Shahih Bukhari dan Muslim, Tafsir Tabari (30 jilid), Tafsir al-Kasysyaf dari Al-Zamakhsyari dan seterusnya. Perdebatan di bidang theologia antara berbagai pemikir “Ilmu Kalam” bertaraf raksasa, seperti Al-Asy’ari, Al Baqillani, Al-Mutaridi, Juhaim dan sebagainya, sepenuhnya bersandar pada karya-karya standar dalam ilmu bahasa yang disebutkan di atas. Humanisme yang muncul dari penyarapan begitu ekstensif dan pengendapan pengetahuan begitu intensif itu pada akhirnya melahirkan raksasa-raksasa pengetahuan di dunia Islam waktu itu: para filosof seperti Al-Kindi, Ibn Sina, dan Al-Razi; sarjana Matematika seperti Al-Khawarizmi, sarjana Geografi seperti Yaqub Al-Humawi, sarjana Gramatika seperti Ibn Malik, Kritikus sastra seperti Al-Mubbarrid (dilestarikan dalam karya monumental 4 jilid berjudul Al-Kamil), dan seterusnya.
Watak utama dari tradisi keilmuan dalam Islam pada pada taraf dininya itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran di atas, dapat diringkas ke dalam ungkapan berikut: kemampuan mendampingkan dua hal yang bertentangan tanpa membuat salah satunya kehilangan identitas semula. Ilmu bahasa berkembang menjadi berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti dikemukakan di atas, demikian pula Ilmu-ilmu Syari’ah. Sesuatu yang sangat kosmopolitan dan eklektik dibiarkan berkembang berdampi ngan, bahkan saling menunjang, dengan disiplin-disiplin ilmu yang memiliki orientasi sangat normatif. Watak utama “bersatu dalam keragaman” (unity in diversity) dari orientasi dasar tradisi keilmuan di masa kejayaan peradaban Islam inilah yang harus dikenal, kalau kita ingin melestarikannya.
Namun, keseimbangan begitu halus (yang sekaligus menjadi benang halus pengikat) antara kedua orientasi elektik dan otomotif tersebut, ternyata tak dapat dipertahankan. Rasionalisme yang akhirnya menjadi buah dari humanisme (mengambil bentuk “gerakan Muktazilah”) bagaimanapun juga lalu tak dapat didamaikan dengan ilmu-ilmu Syari’ah, sebagaimana dilambangkan oleh pembabatan Al-Ghazali dengan karya utamanya, Ihya ‘Ulum al-Din atas watak elektik dari humanisme yang muncul dari ilmu-ilmu bahasa. Walaupun Al-Ghazali berhasil mengalihkan penjagaan kreatifitas dari pemasungan oleh formalisme syari’ah ke tangan tasawwuf, humanisme dalam Islam telah kehilangan sendi-sendi rasional dari kehidupannya. Tasawwuf dengan pendekatan yang mengutamakan immanensi Tuhan, dalam jangka panjang haruslah bergantung kepada syari’ah, sehingga akhirnya juga tidak terhindar dari formalisme yang mematikan kreativitas. Sedangkan transendensi Tuhan, yang akan memberikan jaminan bagi kebebasan manusia untuk merumuskan pola kehidupan yang dikehendakinya, tak akan dapat tumbuh tanpa sendi-sendi rasional dari humanisme yang semua dimiliki Islam di masa puncak kejayaan peradaban dunia.
Pemikiran rasional yang tuntas memang mudah sekali berubah arah menjadi Rasionalisme, seperti terbukti dari sejarah berbagai agama dan aliran filsafat. Namun, penolakan kita terhadap Rasionalisme tetap harus dalam batas-batas yang tidak menghancurkan wawasan rasional dari pemikiran ilmiah kita sendiri. Justru diktum ini yang merupakan kekuatan dari tradisi keilmuan Islam pada masa keemasannya. Para ulama yang sekaligus menjadi ilmuwan kelas satu jelas sekali memahami hal ini secara tuntas, seperti dibuktikan oleh kasus-kasus berikut: penghafal Al-Qur’an (Hafiz) seperti Abu ‘Amir ibn Al-Ala yang sekaligus adalah seorang filolog, sufi seperti Hasan Al-Basri yang menjadi kritikus sastra, ahli fiqh seperti Imam Hanafi yang sekaligus adalah seorang arsitek, dan banyak lagi contoh lain.
Sekali wawasan rasional ditekan dan ditundukkan kepada Syari’ah, maka kekuatan dari tradisi keilmuan lalu hilang. Inilah yang dalam jangka panjangnya menyebabkan kemunduran peradaban Islam, dan akhirnya membawa kaum muslimin kepada kehinaan derajad, sebagai bangsa-bangsa yang terjajah di kemudian harinya, dan hingga kinipun masih terbelenggu oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Kenyataan ini seharusnya menyadarkan kita kepada sebuah kebutuhan akan reorientasi mendasar dalam pemikiran kaum muslimin, yaitu bagaimana menegakkan wawasan rasional dalam kehidupan beragama. Dengan cara seperti itu, tradisi keilmuan dalam Islam akan memperoleh kembali kekuatannya yang telah lama hilang.
Wawasan Rasional
Tradisi keilmuan Islam untuk masa modern ini harus dikembangkan lagi dalam rangka menumbuhkan wawasan rasional itu. Keharusan ini dengan sendirinya memerlukan dari mana kesediaan untuk meninjau permasalahannya secara mendalam. Kalau memang benar wawasan rasional yang harus ditumbuhkan, maka jelas beberapa hal berikut haruslah diberi perhatian khusus :
a. Kecenderungan formalistik yang makin gencar belakangan ini, karena ketakutan akan digusur keimanan oleh modernisasi model Barat, haruslah dijaga tidak mencapai tingkat eksessif;
b. Tidak dapat dibenarkan kecenderungan untuk mengemukakan Islam sebagai alternatif sumir yang bersifat riil bagi ideologi, faham, agama dan aliran pemikiran lain. Kalau hal itu dilakukan, maka Islam tetap akan terisolir dari perkembangan umum kemanusiaan dan kehilangan watak eklektik dari dirinya, padahal watak ini diperlukan untuk mengembangkan wawasan rasional yang dibutuhkan;
c. Secara konsepsional, harus dilakukan kembali perumusan pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk yang utuh dalam kepribadian dan tidak layak diperlukan hanya antara terkeping-keping (misalnya, hanya sebagai obyek legal-formalisme belaka). Dengan demikian, diperlukan upaya merumuskan buah konsep yang lebih multidimensional tentang manusia, dengan wawasan filosofis yang jelas dan bulat:
d. Harus dihindarkan sejauh mungkin upaya membuat penalaran yang dangkal, dalam bentuk mencocokkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Rasul dengan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan modern. Yang harus digali adalah asas-asas ilmiah yang ada dalam Islam, seperti asas keseimbangan antara rasio dan intuisi dan sebagainya, yang dalam pengembangannya akan melengkapi dimensi-dimensi ilmu pengetahuan modern.
Dengan memperhatikan hal-hal di atas, tradisi keilmuan dalam Islam dapat dikembangkan kembali dalam kerangka berikut :
a. Orientasi ilmu pengetahuan yang dikembangkan haruslah ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan hakiki umat manusia akan keadilan struktural yang tuntas dalam kehidupan masyarakat negara-bangsa (nation-state) maupun masyarakat dunia. Kebutuhan hakiki itu dapat berbentuk pengakhiran orientasi serba materialistik dalam kehidupan umat manusia, dapat juga mengambil bentuk lain-lain (seperti pengakhiran dominasi dan hegemoni negara-negara besar dan seterusnya);
b. Wawasan ilmiah dari tradisi keilmuan yang akan dikembangkan itu haruslah memiliki liputan universal, tidak hanya berlaku bagi kaum, muslimin belaka, dan ini berarti keharusan adanya toleransi tuntas, dalam pergaulan antar-pemikiran dan antar-faham. Ini hanya dapat dikembangkan, kalau diberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pikiran paling gila sekalipun kepada semua warga masyarakat, tanpa kecuali ;
c. Haruslah dilakukan pembedaan tajam antara keperluan dan kepentingan Islam sebagai sebuah agama, dari kepentingan institusional lembaga-lembaga yang berdiri “atas nama Islam”. Ini berarti keharusan mengajak lembaga-lembaga yang ada itu untuk tidak selalu mengidentifikasikan kepentingan mereka sebagai kepentingan Islam. Dalam keadaan terdapat kebebasan dari “penafsiran institusional” atas kepentingan Islam, semua pemikiran akan dapat dikemukakan tanpa kecanggungan sama sekali, dan tradisi keilmuan baru akan berkembang dalam kehidupan kaum muslimin.
Mungkin apa yang dikemukakan sebagai sumbangan pikiran di atas terasa agak sumir dan penuh dengan over-simplifikasi, namun dirasa dengan mengemukakannya kita akan dapat memulai dialog yang dewasa dalam meneropong kemungkinan-kemungkinan bagi dinamisasi tradisi keilmuan dalam Islam, setelah sekian abad mengalami kebekuan.