Tentang Masa Depan Intelektual
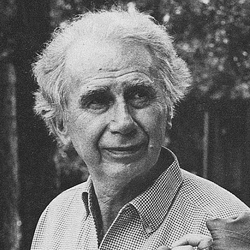
Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid
Pertentangan dasar bukanlah antara kapitalis dan proletar atau petani dan penguasa. Sebuah kelas baru tumbuh: intelektual modern. Penulis buku adalah sosiolog politik di Washington University serta penulis buku-buku teori sosial.
THE FUTURE OF INTELLECTUALS AND THE RISE OF THE CLASS
Oleh: Alvin W. Gouldner, New York, The Seabury Press, sebuah buku Continuum, 1979, 121 halaman dengan bibliografi dan indeks.
KAUM intelektual, sadarilah siapa dirimu”. Slogan ini agaknya layak diterapkan sebagai penyifatan isi buku Gouldner — buku kedua dari triloginya yang berjudul The Dark Side of the Dialectic. Keseluruhan buku ini ditujukan untuk membuktikan kesalahan anggapan kaum Marksis yang berpendapat, bahwa pertentangan dasar abad ini terjadi antara kaum kapitalis dan kaum proletar. Atau, dengan sedikit modifikasi, antara kaum petani dan kelas yang menguasai mereka.
Dilihat dari kacamata Gouldner, semboyan yang relevan dalam pertentangan kelas bukanlah seruan Marx dan Engels yang berbunyi: “kaum buruh sedunia, bersatulah!” Harus dicari semboyan lain.
Antara kelas bawah yang diisap, dan kelas atas yang melakukan pengisapan, menurut Gouldner, muncul sebuah kelompok baru yang tidak mudah dikategorisasikan memihak kepada siapa. Kelompok itu, menurut Gouldner, adalah kaum intelektual modern. Ini dibaginya ke dalam dua kategori kaum intelektual (yang mengutamakan kecakapan) dan kaum inteligensia (yang mengutamakan pengembangan pemikiran).
Kelas Cacat
Poros intelektual dan inteligensia itlah yang dinamai Gouldner ‘kelas baru’ — yang memiliki peranan terpenting dalam dinamika dan pertentangan kelas di abad modern ini. Lawan ‘kelas baru’ adalah kelas lama yang oleh Gouldner dinamai kelas beruang (moneyed class).
Mulanya, ‘kelas baru’ adalah kelompok lebih berpendidikan belaka dari kelas beruang itu sendiri. Tetapi dalam jangka panjang, dengan semakin khususnya pembidangan kecakapan, terjadi kompetisi sengit antara kelas baru yang memegang fungsi pengelolaan modal dan kelas beruang yang hanya memiliki modal secara formal. Mereka, dalam pertarungan berkepanjangan, akan dibuat lemah oleh kelas baru, diredusir menjadi rentenir, penikmat hasil dividen tanpa berwewenang melakukan usaha, dan sebagainya.
Justru dalam fungsi pengelolaan modal itulah terletak sikap moral yang ambivalen dari kelas baru. Di satu pihak. baik karena ketulusan dan kejujur an intelektual mereka maupun karena kebutuhan oportunistik, kelas baru melakukan aliansi dengan kaum buruh dan petani menentang kelas beruang.
Itu misalnya tercermin dalam sejumlah isu yang disitir Gouldner dalam hal. 16-17 kebebasan kampus, perlindungan hak-hak konsumen, pengembangan sistem manajemen yang lebih menghemat sumber, tuntutan pemberian tempat dominan bagi para ahli dan brain trusts dalam penentuan kebijakan umum, pengembangan pamong praja yang independen dari kekuasaan politik, gerakan pelestarian alam dan gerakan kebebasan wanita (women’s lib).
Tetapi, di pihak lain, sebagaimana semua kelas lain dalam perjalanan sejarah, kelas baru ternyata hanya memperju angkan kepentingannya sendiri — sering atas kerugian kaum buruh dan petani.
Gouldner menunjuk pada kelemahan beberapa penyifatan kelas baru sebagai ‘teknokrat penyejahtera’ (Galbraith, Bell, Berle dan Means), ‘kelas memerintah’ (Bakunin, Machajski), ‘pendamping kelas lama’ (Parsons) dan pengabdi kekuasaan (Chomsky dan Zeitlin). Dan sebagai gantinya Gouldner mengajukan konsep kelas baru sebagai kelas cacat (Flawed Universal Class) yang berwatak elitis, mengejar kepentingan sendiri dan menggunakan kecakapan spesialistisnya untuk mengembangkan kekuasaannya sendiri, dan untuk menguasai situasi kerjanya sendiri’ (hal. 7).
Walau memiliki cacat luar biasa dalam dirinya, kelas ini merupakan kelas yang semakin meningkat peranannya, dan memiliki kemungkinan terbesar untuk menumbangkan kelas lama — hal yang sudah tentu menguntungkan kelas buruh dan petani. Sebagai kelas yang memiliki pertentangan internalnya sendiri, yang bersifat mendasar, ia akan mengubah wajah sejarah.
Dari keenambelas ‘tesis’ yang merupakan bab-bab buku ini, tesis pertama memeriksa kelemahan-kelemahan utama ‘Skenario Marksis’: karena revolusi-revolusi abad ini banyak timbul dari kelas petani, dengan sendirinya setelah revolusi berhasil, bukannya pembangunan sosialis yang terjadi — melainkan hanya upaya elite urban untuk menguasai mereka dengan segenap cara. Begitu juga Skenario Marksis ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan, di manakah sebenarnya tempat kaum teoretisi.
Adalah kaum teoritisi yang menimbulkan dan mengarahkan revolusi. Tanpa mereka, yang nantinya mengajukan klaim sebagai pengawal revolusi, kaum petani tidak akan mampu membuat revolusi, melainkan hanya serangkaian pemberontakan. Tidak ada pengalihan pemilikan secara kolektif dalam skala masif — yang menjadi inti revolusi sosial — berlangsung dalam pemberontakan.
Tesis kedua merumuskan hubungan kaum intelektual di satu pihak dan kaum petani dan massa rakyat lainnya di pihak lain. Kaum intelektual menyediakan kerangka yang diperlukan bagi sebuah revolusi. Sedang mereka sendiri berfungsi selaku penengah dan pengawal revolusi guna mendapat basis kekuatan massa rakyat.
Tesis ketiga melihat kedua jenis utama kelas baru yang terlihat dan yang tak terlihat Kelas baru sering harus menyembunyikan diri di balik profesionalisme untuk dapat tinggal hidup di hadapan kekuasaan menindas. Peranan revolusionernya dilakukan hanya secara terselubung, seperti dalam pengembangan isu-isu yang diamati Gouldner di atas.
Tetapi di negara-negara berindustri maju, kaum intelektual berperan sebagai penuntut struktur masyarakat baru la menentang subordinasi dirinya kepada kepentingan kelas beruang. Perjuangan itu mengambil bentuk dua macam menegakkan masyarakat sosialis di negeri-negeri sosialis, dan menciptakan masyarakat berkecukupan (welfare state) di negeri kapitalis.
Mengingat sifatnya yang demikian, kelas baru dengan sendirinya lalu berperan sebenarnya sebagai sebuah burjuasi kultural — yang dikaji dalam tesis kelima. Pemilikannya atas modal kultural sekaligus menyatukan kelas baru dengan kelas pekerja — dan memisahkan keduanya. Yang menyatukan adalah kebutuhan menumbangkan kelas beruang. Yang memisahkan adalah berkembangnya bahasa tersendiri bagi kalangan kelas baru, pendidikan tersendiri dengan sistem reproduksi kelas baru itu sendiri sebagai hasilnya, dan berkembangnya pembidangan lebih jauh di lingkungan kelas baru sendiri.
Ho Chi Minh
Lalu harus dibedakan antara kaum intelektual dan inteligensia, seperti disebut di atas. Juga antara birokrasi gaya lama dan kelompok baru yang dinamai Gouldner sebagai ‘intelegensia staf’ — seperti terjadi di kalangan pemikir militer yang melakukan revolusi untuk menumbangkan kelas beruang di Peru, Portugal dan Ethiopia.
Tak dapat diabaikan juga peranan ‘intelektual revolusioner’ yang dikupas Gouldner dalam tesis kesepuluh. Di Dunia Ketiga, kaum intelektuallah yang memimpin revolusi Chou En-lai, Chu Yeh, Liu Shaochi dan Ho Chi Minh dịkemukakan sebagai contoh. Mereka merupakan lingkungan tersendiri dalam kelas baru Bahkan Marx sendiri seorang intelektuil, dan Marksisme adalah hasil jerih payah melakukan ‘revolusi’ di perpustakaan.
Buku ini menarik untuk dibaca. Banyak pelajaran dapat ditarik darinya — terpenting adalah justru kesadaran semakin mendalam akan kemungkinan yang dapat diraih kaum intelektual kita sendiri dalam perjuangan menegakkan masyarakat yang demokratis, benar-benar adil dan mampu menyejahterakan warganya. Juga untuk menyadari keterbatasan peranan intelektual sendiri.
Pembahasan metodologis dan teoretis lainnya dari buku ini sangat berharga. Sebagai panduan menelusuri literatur tentang pertentangan kelas. Apalagi ia ditulis dari sudut pandangan Hegelian yang tidak cengeng dan romantis, tetapi tetap memiliki kerangka moral yang utuh.